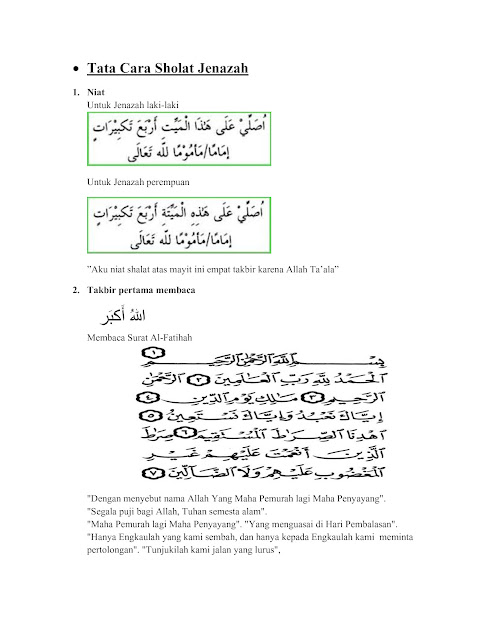KATA PENGANTAR
Segala puji bagi
Allah Swt. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya
yang telah memberi taufiq
dan hidayah-Nya sehingga diktat Fikih-Usul Fikih ini telah selesai penyusunannya. Semoga
dapat membantu pengadaan bahan bacaan
di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah STAI Jam’iyah Mahmudiyah.
Usul fikih merupakan
ilmu alat yang paling mendasar
bagi peminat studi hukum Islam untuk mengantarkan mereka pada pemahaman yang akurat menuju realisasi hasilnya fikih yang benar.
Sementara itu, pada dataran realitas, ada semacam
kesulitan bagi mahasiswa, utamanya
tingkat pemula, mempelajari fikih - usul fikih. Gejala keengganan mendalami bidang ini juga
terasa, karena orang terlanjur merasa
“takut”. Padahal ilmu ini
mengasyikkan dipelajari kalau disikapi secara tepat. Mempertimbangkan argumentasi az-Zuhaili di atas dan menyadari kebutuhan mahasiswa pada penyajian fikih-usul fikih yang mudah
dipahami bagi tingkat pemula, diktat
ini kemudian dihadirkan untuk menyahutinya. Apalagi
bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah
Dan Keguruan yang selalu berkecimpung
di tengah masyarakat, diktat ini Sengaja disesuaikan dengan kurikulum agar pembahasannya sekaligus memenuhi kewajiban akademis, baik bagi mahasiswa maupun dosen pengajar, guna mencapai
Tujuan
Pembelajaran Umum (TPU), yaitu: “Agar mahasiswa mengetahui
dan memahami fikih-
usul fikih sebagai alat untuk mengistinbatkan hukum dari Alquran dan
Hadis dengan menggunakan kaedah-kaedahnya”.
Mengingat luasnya masalah yang bertalian dengan pokok
bahasan yang telah diterapkan, maka pada beberapa bagian ada materi-materi yang
dipersempit dan ada yang dikembangkan yang dianggap erat kaitannya dengan pokok
yang dimaksud
Namun demikian, apa yang dapat dikemukakan dalam buku ini tentunya belum sempurna
jika ditinjau dari sudut luasnya kajian Fikih-Ushul Fikih. Sadar akan
keterbatasan penulis, sumbang saran yang konstruktif akan sangat penulis hargai.
Demikian, semoga bermanfaat.
Tanjung Pura, Januari2020
Penulis,
H. Muamar Al Qadri, M.Pd
DAFTAR ISI
Halaman
|
KATA
PENGANTAR........................................................................................
|
i
|
|
DAFTAR ISI.......................................................................................................
|
iii
|
|
BAB I PENDAHULUAN........................................................................
|
1
|
|
A. Definisi
Ilmu Fikih-Usul Fikih................................................
|
1
|
|
B. Objek
Kajian Fikih-Usul Fikih................................................
|
5
|
|
C. Ruang
Lingkup (Sistematika)..................................................
|
6
|
|
D. Tujuan dan
Kegunaan Fikih dan Usul Fikih............................
|
9
|
|
E. Perbedaan
Fikih dan Usul Fikih...............................................
|
11
|
|
F. Sejarah
dan Perkembangan Fikih-Usul Fikih..........................
|
13
|
|
BAB II HUKUM DAN DALIL -
DALIL HUKUM.................................
.
|
19
|
|
A. Pengertian
Hukum dan Dalil-Dalil Hukum..............................
|
19
|
|
B. Pembagian
Hukum Islam..........................................................
|
19
|
|
1. Taklifi ..................................................................................
|
21
|
|
2. Wad`i
...................................................................................
|
23
|
|
C.
Dalil-Dalil Hukum Islam..........................................................
|
24
|
|
1. Muttafaq `Alaihi (disepakati)...............................................
|
24
|
|
2. Ghairu Muttafaq `Alaihi (tidak
disepakati).........................
|
38
|
|
BAB III IJTIHAD ITTIBA` DAN TAQLID.............................................. ....
|
45
|
|
A. Pengertian
Ijtihad.....................................................................
|
45
|
|
B. Pengertian
Ittiba`.....................................................................
|
48
|
|
C. Pengertian
Taqlid.....................................................................
|
50
|
|
BAB IV KAEDAH-KAEDAH USHULIYYAH........................................
|
53
|
|
A. Pengertian
Kaedah Usuliyyah ................................................
|
53
|
|
B. `Am dan Khas........................................................................
|
53
|
|
C. Amr dan Nahi ........................................................................
|
55
|
|
D. Mutlaq dan Muqayyad..............................................................
|
58
|
|
BAB V KAEDAH-KAEDAH FIQHIYYAH
.............................................
|
61
|
|
A. Definisi
Kaedah Fiqhiyyah.......................................................
|
61
|
|
B. Urgensi Kaedah Fiqhiyyah........................................................
|
62
|
|
|
C.
Perbedaan Kaidah Fiqhiyyah dengan
Kaidah Ushuliyyah........
|
63
|
|
D. Kaedah Asasiyyah....................................................................
.
|
64
|
|
BAB
|
VI
|
MAQASID
AL-SHAR`IYYAH........................................................
|
67
|
|
|
|
A. Pengertian Maqasid al-Shar`iyyah .........................................
|
67
|
|
|
|
B. Pembagian Maqasid
al-Shar`iyyah .........................................
|
67
|
|
|
|
C. Kedudukan Maqasid al-Shar`iyyah…………………………...
|
71
|
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................
BAB
I
PENDAHULUAN
1. Definisi Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih
Pengertian ilmu fikih sebagai rangkaian dari dua buah kata,
yaitu ilmu dan fikih dapat dilihat sebagai nama suatu
bidang disiplin ilmu dari ilmu-ilmu Syari`ah. Kata “ilmu” secara mutlak memuat tiga
kemungkinan arti, pertama, rangkaian permasalahan atau hukum-hukum
(teori-teori) yang dibahas dalam sebuah bidang ilmu tertentu. Kedua, idrak (menguasai)1 masalah-masalah
ini atau mengetahui hukumnya
dengan cara yang meyakinkan. Akan tetapi pengertian seperti ini sesungguhnya
hanya terbatas pada masalah akidah,
adapun dalam hukum-hukum fikih tidak disyaratkan mengetahui dengan
cara demikian, cukup dengan dugaan
kuat saja. Ketiga, pemahaman awal
tentang suatu permasalahan melihat tampilan
luarnya. Misalnya dengan istilah ilmu
nahu, orang akan paham bahwa yang
dibahas adalah sekitar permasalahan kebahasaan seperti mubtada` itu marfu’, atau dengan istilah ilmu
fikih orang lalu paham bahwa pokok bahasannya adalah sekumpulan hukum- hukum syari`ah praktis, dan sebagainya.
Dilihat dari sudut bahasa, fikih
berasal dari kata faqaha (فقه ) yang berarti
“memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahan syar`i, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar`I amali (praktis) yang
1Hans Wer mengulas kata idrak
dengan memberikan arti sebagai reaching,
attaintment, achievement, accompilshment, realization, perception, discernment,
awareness and consciousness (Wer, 1980:279).
penetapannya
diupayakan melalui pemahaman yang mendalam
terhadap dalil- dalilnya yang terperinci
(al-tafsili) dalam
Alquran dan hadis.2 Sedangkan “fikih”
Artinya : Himpunan hukum syara`
tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.
sebagaimana dikemukakan oleh
al-Jurjani4 adalah sebagai berikut:
Artinya: Ilmu tentang
hukum syara` tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.
Hukum syar`i yang dimaksud
dalam defenisi di atas adalah segala perbuatan yang diberi
hukumnya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun
kata `amali dalam defenisi itu dimaksudkan
sebagai penjelasan bahwa yang
menjadi lapangan pengkajian ilmu ini
hanya yang berkaitan dengan
perbuatan (`amaliyah) mukallaf dan tidak termasuk keyakinan atau iktikad (`aqidah) dari mukallaf itu. Sedangkan yang dimaksud
dengan dalil-dalil terperinci
(al-tafshili) adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash di mana satu per satunya menunjuk
pada satu hukum tertentu.5
Sebagai perbandingan, al-Kasani mendefinisikan fikih sebagai ilmu halal dan haram,
ilmu syariat dan hukum. Pengertian seperti ini menggambarkan secara
2Hasbi al-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqh, (Jakarta: CV.
Mulia, 1967), hlm. 17. Lihat juga Pengantar
Ilmu Fiqh, (Jakarta : Proyek Pembinanan Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1981)
hlm. 10, Abd. Al-Wahhab Khallaf, Ilmu
Ushul Fiqh, (Jakarta : Al-Majlis al-A`la al-Indonesia li al-Dakwah al-
Islamiyah, 1972) hlm. 11. Alaiddin Koto, Ilmu
Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah
Pengantar), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.
3Rachmat
Syafe`I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 19. 4Kamal
Mukhtar, dkk., Ushul Fiqh I, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2. 5Alaiddin
Koto, Ibid..
sederhana bidang kajian fikih yang
umumnya bicara tentang halal atau haramnya suatu
perbuatan tertentu. Sementara itu Abu
Hanifah sebagaimana dikutip6, menyebut
fikih sebagai pengetahuan diri tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
Kemudian dijelaskan bahwa ada
satu penekanan yang melekat pada fiqh, yaitu
pencapaiannya yang berdasarkan zann (dugaan kuat) sehingga ulama (terutama usuliyyin) menyebut fikih sebagai bab dugaan (al-fikih min bab az-zunun).
Adapun Kata “Usul
al-fikih” terdiri dari dua kata, yaitu “Usul” dan “al- Fikih” yang dipakai menjadi nama sesuatu tertentu dan kata-kata tersebut tidak terlepas dari makna dasar
setiap kata sebelum disatukan menjadi nama sesuatu tertentu itu.7
Dilihat dari
sudut tata bahasa Arab, rangkaian kata ushul dan fikih tersebut dinamakan tarkib idhafi, sehingga dua kata itu memberi
pengertian ushul bagi fikih, Usul ) أصول) adalah bentuk jamak dari kata asl ( اصو) yang menurut bahasa diartikan
dengan dasar suatu bangunan atau
tempat suatu bangunan.8 Asl berarti
dasar, seperti dalam kalimat “Islam
didirikan atas lima usul (dasar atau fondasi)”. Masih banyak pengertian
yang dapat diambil dari kata asl seperti,
cabang, yang kuat, fondasi suatu bangunan dan seterusnya. Jadi Usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Akan tetapi pengertian yang lazim
digunakan dalam ilmu usul fikih adalah
dalil, yang berarti usul fikih
adalah dalil-dalil bagi fikih.
Sedang menurut istilah, asl dapat berarti dalil (landasan hukum), seperti dalam
ungkapan “asl dari wajibnya salat
adalah firman Allah dan Sunnah Rasul”.
6Wahbah
az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami,
jilid 1, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986) hlm.19.
7Abu al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, (Beirut : Dar
al- Kutub al-Arabi, 1404 H.) hlm. 9
8Muhammad Abu Zahrah, Malik
Hayatuh wa `Ara`uh wa Fiqhuh, (Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby, tt.), hlm. 7
Maksudnya ialah bahwa
dalil yang menyatakan salat itu wajib adalah
ayat Alquran dan Sunnah Rasulullah.
Berdasarkan pengertian tiga kata (ilmu usul fiqh) di atas, maka
pengertiannya sebagai rangkaian kata adalah
mengetahui dalil-dalil bagi
hukum syara’ mengenai perbuatan dan aturan-aturan untuk pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil yang terperinci.9 memberi
pengertian usul fiqh sebagai berikut:
العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة االحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية
Artinya: Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian
hukum- hukum syara` mengenai perbuatan manusia (amaliah) dari dalil-dalil yang terperinci.
Maksud dari kaedah-kaedah itu dapat dijadikan sarana
untuk memperoleh hukum-hukum syara’ mengenai
perbuatan, yakni bahwa kaedah-kaedah tersebut merupakan cara atau jalan yang
harus digunakan untuk memperoleh hukum-hukum syara’, sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan pengertian usul
fikih yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, sebagai berikut:
ِ َية من األدلَة.
القواعد التي يتوصل بها استنباط األحكام الشر
artinya: Himpunan kaidah (norma-norma) yang berfungsi sebagai alat penggalian hukum syara`
dari dalil-dalilnya.
Upaya mendeduksi hukum-hukum fikih dari
indikasi-indikasi yang terdapat dalam sumber-sumbernya merupakan tujuan pokok usul fikih, dan fikih semacam ini
merupakan produk akhir dari usul fikih,
tetapi keduanya merupakan dua hal yang masing-masing berdiri sendiri.
9Abd.
Al-Wahhab Khallaf, op.cit., hlm.12.
Pengertian yang lebih detail dikemukakan oleh Muhammad
Abu Zahrah, ilmu usul fikih adalah ilmu
yang menjelaskan cara-cara yang harus
ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nas syara’ dan dalil-dalil yang
didasarkan kepadanya.10
B.
Objek Kajian Fikih dan Usul Fikih
Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari
sudut hukum syara`.11 Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar : ibadah, muamalah, dan `uqubah.
Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada
pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan
dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji dan
lain sebagainya.
Bagian muamalah mencakup
hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, sewa menyewa, pinjam
meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan
persoalan munakahat dan siyasah.
Bagian `uqubah mencakup
segala persoalan yang menyangkut tindak
pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan,
pemberontakan dan lain-lain.
Bagian ini juga
membicarakan hukuman-hukuman, seperti qisas, had, diyat dan ta`zir. 12
Objek kajian Usul
Fikih Berdasarkan definisi yang
dikemukakan para ulama usul fikih di atas, seorang ahli fikih dan usul fikih dari Syiria, Wahbah az-Zuhaili13 mengatakan bahwa yang
menjadi objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil (sumber- sumber) hukum syar’i yang bersifat umum yang
digunakan dalam menemukan
10Sekalipun Ali Hasaballah ketika menawarkan definisinya
pada ilmu ini menyebut istilah
‘Ilm al-Usul, kiranya tidak
ada perbedaan sebab maksudnya sama persis.
11Abdul
Wahhab Khallaf, op.cit., hlm. 12.
12Alaiddin
Koto, op.cit., hlm. 5.
13Wahbah
az-Zuhaili, op.cit., hlm.27.
kaidah-kaidah yang global dan hukum-hukum syar’i yang digali dari dalil-dalil
tersebut. Pendapat ini sedikit berbeda dengan kebanyakan ahli usul yang biasanya membatasi
hanya pada dalil-dalilnya saja, sementara Wahbah az-Zuhaili kelihatannya lebih teknis dan lebih operasional.
Pembahasan tentang
dalil ini adalah secara global, baik tentang macam-
macamnya, rukun atau syarat,
kekuatan dan tingkatan-tingkatannya.
Sementara dalam ilmu usul fikih tidaklah dibahas satu
persatu dalil bagi setiap perbuatan.
C.
Ruang Lingkup (Sistematika) Fikih dan Usul Fikih
Ruang lingkup fikih secara umum mencakup dua bidang, yaitu fikih
ibadah yang mengatur
hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fikih muamalah yang
mengatur hubungan manusia dengan
manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fikih selain
persoalan ubudiyah, seperti
ketentuan- ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah dan lain-lain.14
Sementara itu,
Musthafa A.Zarqa membagi kajian fikih mejadi enam bidang,
yaitu :
1)
Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang
ubudiyah, seperti shalat, puasa,
dan ibadah haji, inilah yang kemudian
disebut fikih ibadah.
2)
Ketentuan –ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan,
perceraian, nafkah, dan ketentuan
nasab. Inilah yang kemudian
disebut ahwal as-syakhsiyah.
14Hafsah,
Pembelajaran Fikih, (Bandung:
Citapustaka media, 2013) hlm. 5.
3)
Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial
antara umat Islam dalam konteks
hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual beli,
sewa menyewa, dan gadai. Bidang ini
kemudian disebut fikih muamalah.
4)
Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi
terhadap tindak kejahatan kriminal.
Misalnya, qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini disebut dengan fikih jinayah.
5)
Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Misalnya, politik dan
birokrasi. Pembahasan ini dinamakan
fikih siyasah.
6)
Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan
kehidupan sosial. Bidang ini
disebut Ahkam khuluqiyah. 15
Ruang lingkup pembahasan Usul fikih dinyatakan oleh
al-Amidiy, sebagai berikut :
ولما كانت مباحث األصللين فى علم االصل التخرج عن احلا األدلة الملصلة الى االحكام الشرعية
المبحلث عنها فيه، واقسامها، واختالف مراتبها وكيفية استثمار االحكام الشرعية عنها على وجه كلى 16.
Pernyataan diatas menyebutkan bahwa ruang lingkup
pembahasan usul fikih tidak keluar dari pembahasan dalil-dalil untuk memperoleh
hukum syara`, pembahasan pembagian dalil-dalil, perbedaan tingkatan dan
urutannya, dan upaya mendeduksi hukum-hukum syari`at dari dalil-dalilnya.
Secara garis
besarnya ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari:
15Dede
Rosyada, Hukum Islam dan pranata Sosial,
(Jakarta : Raja Grafindo, 1992) hlm. 65-
76.
16Abu
al-Hasan `Ali ibn Muhammad al-Amidi, op.cit.,
hlm. 10.
1.
Pembahasan dalil-dalil sam`iyyat (Alquran dan Sunnah) dalam rangka penetapan hukum-hukum syara`
2.
Pembahasan hukum-hukum syara` dari
segi penetapan dari dalil-dalilnya.
Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari :
1.
Hukum-hukum syar`i
2.
Yang menetapkan bukum, yaitu Allah Swt. dan cara-cara
mengetahui hukum- hukum Allah, yaitu mengetahui dalil-dalil dan mengetahui sumber-sumber syari`at untuk
mengetahui hukum-hukum syara`.
3.
Cara-cara istinbat.
4.
Al-Mustanbit (mujtahid).
Pengetahuan tentang kaedah-kaedah interpretasi cukup
penting dalam memahami nas hukum
secara tepat, karena memahami nas Alquran
dan sunnah secara tidak tepat menimbulkan tidak adanya hukum yang dapat
dideduksi dari padanya, terutama bila nas itu bukan merupakan dalil yang
berdiri sendiri. Pemahaman yang memadai tentang metodologi dan kaedah-kaedah
interpretasi lebih diharapkan akan sampai pada ketepatan pemakaian nalar dalam
suatu sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. Dengan demikian akan
tercapai tujuan puncak usul fikih, yaitu untuk sampai pada pengetahuan
hukum-hukum syar`iyyah dan dengan
hukum-hukum syar`iyyah itulah
diperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Usul fikih juga memuat
pokok bahasan tentang sumber-sumber hukum syara’ baik yang disepakati kehujjahannya, yaitu Alquran
dan Sunnah, maupun yang diperselisihkan sebagai dalil hukum syara’, seperti istihsan,
maslahah
mursalah,
istihsab dan
lain-lain. Dalam pembahasan tentang Alquran dan Sunnah, usul fikih melakukan
kajian dari segi lafaznya baik dalam bentuk amr,
nahy, ‘am, khas, mutlaq dan muqayyad.
Lebih lanjut usul fikih membahas lafaz amr
dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan
wajib, lafaz nahy dari segi pengertian aslinya yang menunjukkan haram,
lafaz
umum (‘am) yang menunjukkan
terhadap semua yang dapat dimasukkan
dalam pengertian tersebut, begitu juga
lafaz-lafaz lainnya
harus digunakan terhadap sasaran yang
ditunjukkannya. Kesemuanya dituangkan dalam kaidah-kaidah yang disebut
Kaidah Hukum Umum (Hukum Kuli) yang diambil
dari dalil kulli17
Di samping ruang
lingkup tersebut di atas, usul fikih mempunyai
sasaran dasar, yaitu mengatur ijtihad dan menuntun faqih
dalam upaya mendeduksi hukum
dari sumber-sumbernya. Kebutuhan
terhadap usul fikih merupakan ilmu yang
sangat penting ketika
orang-orang yang tidak memenuhi syarat
berusaha melakukan ujtihad, sehingga akibat terjadinya kekeliruan
dalam pengeluaran hukum dapat dihindari.
D.
Tujuan dan Kegunaan fikih dan Usul Fikih
Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai dari ilmu fikih adalah penerapan hukum syariat kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan
maupun perkataannya.18 Dengan mempelajarinya
orang akan tahu mana yang diperintah
dan mana yang dilarang, mana yang sah dan mana yang batal,
mana yang halal dan mana yang haram,
dan lain sebagainya. Ilmu ini diharapkan muncul sebagai rujukan
bagi para hakim pada setiap keputusannya, bagi para ahli hukum di

2-3.
17M.Asywadie
Syukur, Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul
Fikih, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1990),
18Abdul
Wahab Khallaf, op.cit., hlm. 14.
setiap pendapat dan gagasannya, dan juga bagi setiap mukallaf pada
umumnya dalam upaya mereka mengetahui hukum syari`at dari berbagai masalah yang
terjadi akibat tindak tanduk mereka sendiri.19
Kegunaan fikih adalah untuk merealisasikan dan melindungi
kemaslahatan umat manusia,
baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama dapat
diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu : dharuriyyat (primer) hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyyat (stabilitas sosial).
Usul fikih mengandung dua tujuan pokok, yaitu: Pertama,
menerapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan
oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan bahwa sesuatu
masalah baru; yang tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. Kedua, mengetahui lebih mendalam
bagaimana upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah, sehingga berbagai masalah yang muncul dapat ditetapkan hukumnya20
Adapun
kegunaan usul fikih adalah sebagai berikut:
1.
Untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi ulama-ulama mujtahid dalam mengistinbatkan hukum.
2.
Untuk memantapkan
pemahaman dalam mengikuti pendapat ulama
mujtahid, setelah mengetahui alur berpikir yang dipergunakannya.
3.
Dengan memahami metode
yang dikembangkan para mujtahid,
dapat menjawab berbagai kasus-kasus
hukum yang baru.
19Alaiddin
Koto, op.cit., hlm. 10.
20Abdul
Wahab Khallaf, op.cit., hlm. 14-15.
4.
Dengan memahami usul
fikih, hukum agama terpelihara dari penyalahgunaan dalil.
5.
Berdaya guna untuk memilih
pendapat yang terkuat di
antara berbagai pendapat, berikut dengan alasan-alasannya.
Bila dicermati, penjelasan di atas mengarah pada
dua kelompok orang, yakni jika memang berkecimpung secara praktis dalam hukum
Islam, maka memahami
usul fikih akan sangat bermanfaat bagi para mujtahid untuk meminimalisir kesalahan mengambil keputusan hukum. Bagi
peminat studi hukum Islam khususnya, juga bagi segenap umat Islam umumnya, usul fikih membuat kita dapat beramal ilmiah.21
E.
Perbedaan Fikih dan Usul Fikih
Dari uraian di atas terlihat
perbedaan yang nyata antara ilmu fikih dan ilmu usul
fikih. Kalau ilmu fikih berbicara
tentang hukum dari sesuatu perbuatan,
maka ilmu ushul fikih bicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Atau dilihat dari sudut aplikasinya,
fikih akan menjawab pertanyaan “apa hukum dari suatu
perbuatan”, dan ushul fikih akan menjawab pertanyaan “bagaimana proses atau cara menemukan
hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan
tersebut”. Oleh karena itu, fikih lebih bercorak produk sedangkan ushul fikih lebih bermakna metodologis. Dan oleh sebab itu, fikih terlihat
sebagai koleksi produk hukum, sedangkan
ushul fikih merupakan koleksi metodis
yang sangat diperlukan untuk
memproduk hukum.22
Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara usul fikih
dengan fikih, maka terlebih dahulu dikemukakan ruang lingkup fikih. Adapun
ruang lingkup
21Wahbah
az-Zuhaili, op.cit., hlm. 31.
22Prof.Dr.H.Alaiddin
Koto, M.A., ibid., hlm. 4-5.
pembahasan fikih meliputi
semua perbuatan mukallaf, yakni perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan,
dengan keluarga dengan masyarakat dan
negara, baik berupa ketaatan maupun pelanggaran.
Untuk menetapkan hukum perbuatan mukallaf tersebut, baik menyangkut
ibadah, mu’amalah, munakahat maupun
jinayah, ulama fikih menyesuaikan/mengembalikannya kepada hukum
kulli yang ditetapkan oleh
usul fikih. Begitu juga dalil yang
digunakan oleh ulama fikih sebagai dalil juz`i, harus disesuaikan dengan
dalil-dalil yang dibuat oleh ulama usul fikih.23
Dapat dipahami bahwa usul fikih membahas dalil kulli yang
menghasilkan hukum kulli;
sedang ulama fikih menjadikannya sebagai
dasar/rujukan dalam kasus- kasus
tertentu. Sebagai contoh: usul fikih menetapkan
“al-amr li al-wujub”, maka semua nas yang menunjukkan amr adalah menunjukkan wajib. Amr adalah dalil kulli, sedang wujub (ijab) adalah hukum kulli. Dalam Alquran surah
al-Ma`idah ayat 1 terdapat amr untuk menepati janji. Nas
ayat tersebut adalah dalil
juz`i, sedang hukum yang dikandungnya (wajib menepati janji) adalah hukum juz`i.
Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup usul fikih adalah sumber- sumber/dalil-dalil hukum, jenis-jenis hukum, cara istinbat hukum
dan ijtihad dengan berbagai permasalahannya. Dalam kaitan ini usul
fikih membahas dalil kulli yang menghasilkan hukum kulli. Sedang fikih, ruang lingkupnya adalah semua perbuatan mukallaf dari segi hukum syara’. Dalam hubungan ini fikih membahas dalil juz`i yang
menghasilkan hukum juz`i.
Cukup jelas bahwa usul fikih menjadi dasar hukum fikih.
23M.Asywadie
Syukur, op.cit., hlm. 3
F.
Sejarah dan Perkembangan Fikih dan
Usul Fikih
Pertumbuhan usul fikih
tidak terlepas dari pertumbuhan fikih
sejak periode Rasulullah saw sampai tersusunnya usul fikih
sebagai suatu ilmu. Ketika Rasulullah
masih hidup tuntunan yang diperlukan
dan jalan keluar untuk berbagai masalah diselesaikan dengan baik, baik melalui
wahyu maupun putusan langsung dari
Rasulullah. Ketika itu sumber hukum Islam hanya Alquran
dan Sunnah. Hukum yang ditetapkan dalam Alquran atau Sunnah terkadang dalam bentuk jawaban dari
suatu pertanyaan atau karena munculnya suatu
kasus.
Dalam beberapa
kasus, Rasulullah saw menetapkan
hukum dengan menggunakan qiyas; antara lain ketika menjawab pertanyaan
Umar bin Khattab, apakah batal puasa seseorang yang mencium isterinya. Rasulullah
saw bersabda (maknanya) “Apabila kamu
berkumur-kumur dalam keadaan
puasa apakah puasamu batal? Umar menjawab: Tidak apa-apa (tidak batal), Rasulullah
saw bersabda: Teruskan puasamu” (H.R. Bukhari,
Muslim dan Abu Daud).
Cara Rasulullah saw dalam menetapkan hukum seperti
dalam hadis di atas merupakan cikal bakal munculnya ilmu usul fikih, bahkan
para ulama usul fikih menyatakan bahwa keberadaan usul fikih bersamaan dengan
munculnya hukum fikih sejak periode Rasulullah saw.24
Dekatnya para sahabat
dari masa hidup nabi dan pengetahuan mereka yang mendalam mengenai berbagai peristiwa memberikan
kewenangan kepada mereka untuk memutuskan masalah-masalah praktis
tanpa adanya kebutuhan mendesak terhadap metodologi.
24Nasrun
Haroen, Ushul Fikih 1, (Jakarta:
Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.7.
Pada periode sahabat
muncul bermacam peristiwa yang belum pernah
terjadi pada masa Rasulullah saw. Untuk menetapkan hukumnya
para sahabat harus berijtihad. Dalam berijtihad, adakalanya dihasilkan kesepakatan pendapat di antara para sahabat yang kemudian
dinamakan ijma’
dan terkadang terjadi perbedaan pendapat yang
dinamakan asar.25 Dengan
demikian, munculnya usul fikih telah berlangsung sejak zaman Rasulullah saw, semakin jelas
dan eksis pada
masa Sahabat. Penggunaan usul fikih semakin
berkembang pada masa Sahabat,
oleh tuntutan peristiwa yang semakin beragam dan bertambah rumit.
Setelah Rasulullah saw wafat, ijtihad para sahabat sudah merupakan sumber hukum. Di antara contoh
ijtihad sahabat periode sahabat bahwa
Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada seseorang yang
mencuri karena kelaparan, mengingat yang bersangkutan mencuri karena
darurat/terpaksa.26
Contoh lain, ketika
Ali bin
Abi Thalib berpendapat bahwa
hukuman orang yang meminum
khamar disamakan dengan hukuman orang yang melakukan qazab (menuduh orang lain berbuat zina), yaitu 80 kali
dera. Ali bin Abi Thalib
mengemukakan argumentasi bahwa orang
yang minum khamar akan mabuk, orang yang mabuk akan mengigau. Bila sudah mengigau, ucapannya tidak terkontrol dan akan menuduh orang lain berbuat zina.27
Pada periode sahabat sering terjadi perbedaan pendapat
(perbedaan ijtihad) dalam menetapkan
hukum suatu masalah; antara lain tentang ‘iddah
seorang wanita yang sedang hamil dan suaminya meninggal. Menurut Umar bin
Khattab, ‘iddahnya sampai lahir anak
berdasarkan Alquran surah at-Thalaq ayat
4. Sedang menurut Ali
25M.Asywadie
Syukur, op.cit., hlm. 5. 26Kamal
Mukhtar, dkk., op.cit., hlm. 13. 27Nasrun
Haroen, op.cit., hlm. 8.
bin Abi Thalib dipilih ‘iddah
yang paling lama di antara ‘iddah yang
hamil dengan ‘iddah kematian
suami (4 bulan 10 hari menurut surah al-Baqarah ayat 234), yakni bila
lahir anak sebelum 4 bulan 10 hari maka ‘iddahnya harus ‘iddah kematian suami (4
bulan 10 hari), tetapi bila sesudah
4 bulan 10 hari, anak belum lahir maka
‘iddahnya harus sampai lahir anak.28
Hasil-hasil ijtihad sahabat pada periode ini belum dibukukan sehingga belum dapat dianggap sebagai ilmu, hanya sebagai pemecahan masalah terhadap kasus yang mereka
hadapi. Oleh sebab itu hasil ijtihad
mereka belum disebut fikih/usul fikih. Pada periode sahabat, sumber-sumber hukum Islam adalah Alquran, Sunnah dan ijtihad sahabat. Memasuki masa tabi’in, tabi’ut tabi’in dan imam-imam mujtahidin (abad kedua dan ketiga Hijriyah), daerah yang dikuasai umat Islam semakin luas
dan cukup banyak bangsa yang
non Arab memeluk agama Islam. Dengan demikian
kemungkinan munculnya berbagai kasus yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya
semakin besar.
Mengingat banyaknya kejadian dan problem yang muncul ke
permukaan yang perlu mendapat penyelesaian
hukum, maka ulama-ulama tabi’in dan imam- imam mujtahidin terpanggil melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum masing-
masing kasus tersebut. Pada
kurun ini mereka bukan hanya membahas
hukum tentang kejadian/peristiwa
yang muncul, bahkan mereka perluas mencakup kasus- kasus yang mungkin terjadi
pada masa-masa mendatang; sehingga pembahasan hukum fikih cukup luas.
28Muhammad al-Khudari, Tarikh al-Tasyri` al-Islamy, (Mesir:
al-Maktabat al-Tijariyat al- Kubra, 1965), hlm. 120.
Pada periode ini telah
dimulai gerakan pembukuan fikih, Sunnah dan ilmu- ilmu lainnya. Dalam
menuliskan pendapat tentang hukum-hukum fikih mereka lengkapi dengan dalil-dalil pendapat
tersebut baik dari Alquran atau dari Sunnah maupun sumber-sumber lainnya seperti ijma’,
qiyas, istihsan, mashlahah mursalah dan
lain-lain.
Pada masa ini, ulama-ulama
yang berkecimpung dalam ilmu fikih (digelar
fuqaha) dan ilmu pengetahuan mereka disebut fikih.
Tercatat dalam sejarah hukum Islam bahwa yang pertama sekali mengambil
inisiatif membukukan hukum fikih adalah Imam Malik bin Anas dalam kitabnya “Muwatta”. Dalam kitab ini beliau mengumpulkan hadis-hadis sahih (menurut pandangannya), fatwa-fatwa sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in.
Berarti Muwatta Imam Malik29 adalah kitab hadis dan
fikih.30 Kitab ini menjadi
pegangan ulama-ulama Hijaz.
Kemudian muncul
Imam Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah menyusun beberapa
kitab fikih yang menjadi pegangan ulama-ulama
Irak. Muncul pula Imam Muhammad bin
al-Hasan (sahabat Abu Hanifah)
menulis kitab “Zahiru ar Riwayat as Sittah” yang
dikumpulkan oleh al-Hakim al-Syahid
dalam kitabnya “al-Kafi”, disyarahkan
oleh as-Sarkhasi dalam kitabnya
“al-Mabsut” sebagai rujukan mazhab Hanafi.
Berikutnya al-Imam Muhammad bin
Idris al-Syafi’i di Mesir menyusun kitab “al-Umm” yang menjadi pegangan
mazhab Syafi’i. Pada kitab-kitab yang disusun oleh Imam-imam mujtahid tersebut
di atas, tercantum dalil-dalil hukum
serta wajah istidlalnya sebagai suatu bagian
dari Ilmu usul fikih dengan catatan
belum merupakan ilmu tersendiri.
29Imam Malik sendiri memang dikenal sebagai pakar, baik pada ilmu hadis maupun fikih.
30Muhammad Abu Zahrah, op.cit., hlm. 260
Para ahli usul
fikih menganggap bahwa yang
mula-mula mengumpulkan dan menyusun ilmu Usul fikih
adalah Imam Syafi’i dalam
kitabnya “al-Risalah”.31
Ulama-ulama yang muncul sesudahnya berusaha melanjutkan dan menyempurnakan karya Imam Syafi’i ini,
seperti Ahmad bin Hanbal, ulama-ulama
Hanafiyah,
Malikiyah maupun Syafi’iyah.32
Imam Syafi`i memiliki kekayaan pemikiran di bidang
hukum dan melakukan pendalaman argumentasi mengenai masalah-masalah
metodologis, tetapi karya-karya yang telah ada tidak terlepas dari perbedaan
pendapat yang harus di saring melalui pedoman-pedoman yang disusun oleh Imam
Syafi`i dalam teori hukumnya.
Ditulisnya kitab
ar-Risalah yang secara khusus membahas tentang
Usul fikih yang diakui secara luas bahwa
kitab tersebut merupakan karya otoritas
pertama dalam bidang usul fikih, karena tepatlah apabila
dikatakan bahwa fikih mendahului
usul fikih,
sebab sepanjang abad pertama
tidak ada kebutuhan yang mendesak terhadap usul fikih, dan baru abad kedua
perkembangan-perkembangan penting terjadi
di bidang ini.
Dengan meluasnya
wilayah Islam, Imam Syafi`i
menjumpai kontroversi
antara ahli hukum Madinah dan ahli hukum Iraq, yang dikenal
sebagai Ahl al-Hadis dan Ahli al-Ra`y. Imam Syafi`i mengkhawatirkan
tercemarnya kemurnian syari`at Islam
dan bahasa Alqur`an, maka disusunnyalah kitab al-Risalah, yang merumuskan pedoman ijtihad dan menguraikan kaedah-kaedah Usul fikih.
31Abdul Halim
al-Jundi (1966:273-293),
mengelaborasi latar belakang Syafi’i yang memungkinkannya
menjadi wadi’ al-usul
dalam banyak halaman bukunya, dan secara khusus
membahas dan menunjukkan sistematisasi al-Risalah
yang membuktikan kitab tersebut pantas disebut sebagai kitab usul fikih
pertama.
32Abdul Wahab Khallaf, op.cit.,
hlm. 15-17.
Imam al-Raziy menyatakan bahwa kesepakatan tentang
penyusun Usul fikih yang pertama ialah Imam Syafi`i, dialah yang menyusun
bab-babnya, menjelaskan urutan dalil dari segi kekuatan dan kelemahannya.33
Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa yang pertama menyusun Usul
fikih ialah Imam syafi`i, yang
ditulisnya dalam al-Risalahnya,
membicarakan amr, nahy, bayan, khabar, naskh dan kemudian Fuqaha` Hanafiyyah mentahqiq qawa`id tersebut, demikian pula
dengan mutakallimin.34
Pada mulanya kitab
yang ditulis oleh Imam Syafi`i
mengenai Usul fikih tidak disebutnya al-Risalah,
tetapi dinamakannya dengan al-Kitab, dan dinamakan al- Risalah pada masanya, karena disampaikannya kepada `Abd al- Rahman ibn Mahdiy.35
Imam al-Syafi`i menulis al-Risalah dua kali, pertama sebelum beliau pergi ke Mesir, yang dikenal
dengan al-Risalah al-Qadimah.
Dan yang kedua pada saat beliau berada
di Mesir, yang dikenal dengan al-Risalah al-Jadidah. Yang ditemukan sekarang hanyalah al-Risalah al-Jadidah, dan merupakan kitab pertama yang ditulis dalam Usul fikih.
BAB II
HUKUM DAN DALIL-DALIL HUKUM
A.
Pengertian Hukum
Para ahli ushul menta`rifkan
hukum dengan :
خطاب هللا المتعلق بأفعا المتكلفين طلبا أوتخييرا
أو
وضعا

hlm.55.
33Fakhruddin
ar-azi, Al-Mahsul fi ilmi Ushul al-Fiqh, (Beirut
: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988),
34Ibn
Khaldun, Mukaddimat, ( t.t.: Maktabat
Mustafa Mahmud, t.th.) hlm. 455.
35Al-Syafi`I,
al-Risalah, (Mesir : Syirkah Ma`tabah
wa Mathba`ah Mustafa al-Baaby al-
Khalaby wa Auladih, 1970), hlm. 12.
Artinya : Perintah Allah Swt. yang berhubungan dengan
perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan ( perintah dan larangan) atau pilihan
(kebolehan) atau wadh`i (menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan
penghalang bagi suatu hukum).
Dari definisi di atas menunjukkan bahwa yang
menetapkan hukum itu adalah Allah Swt. hanya Allah hakim yang maha tinggi dan
maha kuasa, Rasulullah penyampai hukum-hukum Allah kepada manusia. Oleh karena
Allah yang menetapakan hukum, maka sumber hukum yang pertama dan paling utama
adalah wahyu Allah yaitu Alquran, kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum
yang ke dua dan sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad.
B. Pembagian
Hukum Islam
Pada dasarnya hukum Islam
dibagi menjadi lima dasar yaitu :
1)
Wajib (fardhu)
Wajib (fardhu) adalah suatu keharusan, yakni segala
perintah Allah Swt. yang harus kita kerjakan. Di bawah ini ada beberapa pembagian
dalam hukum Islam yang disebut wajib (fardhu) :
a.
Wajib Syar`i adalah
suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendatangkan pahala, sebaliknya jika
ditinggalkan terhitung dosa. Contohnya salat lima
waktu sehari semalam.
b.
Wajib Akli adalah
suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau
rasional. Contohnya adanya alam ini menunjukkan ada yang menciptakan.
c.
Wajib Aini adalah
suatu ketetapan yang harus
dikerjakan oleh setiap muslim antara lain salat
lima waktu, salat jum`at, puasa wajib bulan Ramadhan dan lain sebagainya.
d.
Wajib Kifayah adalah
suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka
orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Akan tetapi jika tidak ada
yang mengerjakannya, maka berdosalah semuanya. Contohnya adalah mengurus
jenazah mulai dari memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan memakamkannya.
e.
Wajib Mukhayyar adalah
suatu kewajiban yang boleh dipilih salah satu dari
bermacam pilihan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan. Contohnya
tebusan apabila kita berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan,
boleh memilih antara memerdekakan hamba atau berpuasa dua bulan berturut-turut
atau memberi makan enam puluh orang miskin.
2)
Sunnah
Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan akan
mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Dibawah ini ada beberapa
pembagian dalam hukum Islam yang disebut sunnah :
a.
Sunnah Muakkad adalah
sunnah yang sangat dianjurkan. Misalnya, salat tarawih dan salat Idul Fitri.
b.
Sunnah Ghairu
Muakkad adalah sunnah biasa. Misalnya, memberi salam kepada orang lain, dan puasa pada hari senin kamis.
c.
Sunnah Haiah adalah
perkara-perkara dalam salat yang sebaiknya dikerjakan, seperti mengangkat kedua
tangan ketika takbir, mengucap Allahu Akbar ketika ruku`, sujud dan sebaginya.
d.
Sunnah Ab`ad adalah
perkara-perkara dalam salat yang harus dikerjakan, dan kalau terlupakan maka harus menggantinya dengan sujud sahwi,
seperti membaca tasyahud awal dan sebagainya.
3)
Haram
Haram adalah suatu perkara yang dilarang
mengerjakannya, seperti minum- minuman keras, mencuri, judi dan lain
sebagainya. Apabila dikerjakan terhitung dosa, sebaliknya jika ditinggalkan
memperoleh pahala.
4)
Makruh
Makruh adalah sesuatu hal yang tidak
disukai/diinginkan. Akan tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa, dan jika
ditinggalkan berpahala, seperti merokok, dan lain sebagainya.
5)
Mubah
Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan
atau ditinggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa.
1.
Taklifi
Hukum Taklifi ialah
hukum yang : 1) menuntut mukallaf melakukan
perbuatan. 2) menuntut mukallaf meninggalkan
perbuatan, atau 3) menuntut mukallaf memilih
antara melakukan atau meninggalkan perbuatan.
2.
Macam-macam hukum
taklifi
Berdasarkan isi tuntutannya berikut ini macam-macam
hukum taklifi adalah sebagai berikut
:
1)
Contoh hukum taklifi
yang menuntut mukallaf untuk melakukan suatu
perbuatan. Berpuasa di bulan Ramadhan, seperti terlihat jelas dalm QS.
al-Baqarah/2: 183.
ياأيها الذين أمنلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقلن ( البقرة
: 381 ) berpuasa kamu atas Diwajibkan ! beriman yang orang-orang Wahai : Artinya
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa’.
·
Melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Cermati QS. Ali Imran/ 3:97.
فيه أيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن
) 79 : عمران ا( . العالمين عن غنى هللا Artinya : Dan diantara
kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah
yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan
perjalanan kesana.
2)
Contoh hukum taklifi yang menghendaki mukallaf untuk
meninggalkan perbuatan, makan bangkai, darah, dan daging babi. Seperti tertera
dalam QS. al-Maidah /5:3.
.... الخنزير ولحم والدم الميتة عليكم حرمت Artinya
: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.
·
Berkata tidak sopan kepada kedua orang tua, seperti
tersurat dalam QS. al- Isra`/17:23
.أف لهما تق فال Artinya: Maka sekali-kali
janganlah engkau mengatakan kepada keduanya
perkataan
ah”.
Dua contoh ayat tersebut berisi larangan yang tegas, sehingga kita tidak
diperbolehkan mengerjakannya.
3)
Contoh hukum taklifi yang membebaskan mukallaf untuk
memilih antara mengerjakan atau meninggalkan
perbuatan.
·
Seusai melaksanakan salat Jum`at, kita dibebaskan
untuk bertebaran atau berdiam diri di rumah. Lihat surah al-Jumu`ah/62:10
berikut :
فإذا قضيت الصالة فانتشروا فى األرض
وابتغلا من
فض هللا واذكروا
هللا كثيرا لعلكم تفلحلن )31( bumi. di kamu bertebaranlah maka dilaksanakan, telah salat Apabila Artinya:
·
Mengqasar salat ketika bepergian jauh seperti tertera
dalam QS. an- Nisa`/4:101 berikut :
وإذا ضربتم فى األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين
مبينا
عدوا لكم كانلا Artinya:
Dan
apabila
kamu
bepergian
di
bumi,
maka
tidaklah
berdosa
kamu
mengqasar
salat, jika kamu takut diserang orang kafir.
Berdasarkan ketegasan isi tuntutannya, melihat
definisi di atas, maka hukum taklifi bisa berupa tuntutan (thalabun), Meninggalkan (tarkun) atau memilih (takhyirun). Sementara isi ketiga hal
tadi bisa jadi disampaikan tegas (sharih)
atau tidak tegas. Jika tuntutan disampaikan secara tegas maka menjadi haram, jika tuntutan
meninggalkan disampaikan secara tidak tegas maka
menjadi makruh, jika tuntutan memilih antara melakukan atau meninggalkan
maka menjadi mubah.
2. Wadh`i
Hukum wadh`i ialah
hukum yang menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab adanya yang lain, atau syarat
bagi sesuatu yang lain, atau penghalang (mani`)
adanya sesuatu yang lain. Jadi, jenis hukum wadh`i
adalah sebab, syarat dan penghalang (mani`).
1.
Sebab ialah sesuatu yang
oleh syari` (pembuat hukum, Allah) dijadikan sebagai sebab adanya
sesuatu yang lain yang menjadi
akibatnya. Ketiadaan sebab menjadikan sesuatu yang
lain menjadi tidak ada. Dalam hukum, keberadaan sebab bersifat mutlak.
Ketiadaan sebab menjadikan hukum tidak ada. Contohnya, kewajiban salat menjadi
sebab kewajiban mengambil wudu`, mencuri menjadi sebab adanya hukum potong
tangan, atau orang yang berhasil memenangkan peperangan menjadi sebab kebolehan
merampas harta benda musuh.
2.
Syarat ialah sesuatu yang
tergantung kepadanya adanya hukum. Dengan tidak adanya syarat, hukum pun
menjadi tidak ada. Misalnya, kemampuan
melakukan perjalanan ke Baitullah merupakan syarat adanya kewajiban haji
bagi seorang mukallaf, kehadiran saksi dalam akad pernikahan merupakan syarat
bagi sahnya akad nikah dan wudu sebagai syarat untuk sahnya shalat.
3.
Penghalang (mani`)
ialah sesuatu yang keberadaannya
dapat meniadakan atau membatalkan hukum. Mani`
hanya muncul ketika sebab dan syarat
itu telah tampak secara jelas. Contohnya, si anak adalah ahli waris dari orang
tuanya, namun, ia bisa tidak
mendapatkan harta warisan dari orang
tuanya karena ada penghalang (mani`).
Penghalang itu bisa berupa kemurtadan si anak atau kematian orang tuanya yang
disebabkan pembunuhan oleh si anak.
C.
Dalil hukum Islam
Dalil secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu yang
bersifat material maupun yang bersifat non material.Sedangkan menurut istilah
dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam
memperoleh hukum syara` yang bersifat
praktis, baik yang kedudukannya qath`i (pasti)
atau dzanni (relatif).
Dalil ditinjau dari segi asalnya terbagi dua :
a.
Dalil Naqli yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash
langsung. Yaitu Alquran dan Hadis. Dalil naqli yang bersumber dari Alquran ini
merupakan dalil yang sudah jelas dan kebenarannya tidak diragukan lagi, karena
berasal dari Allah Swt. dan dijamin
kemurnian dan keasliannya. Demikian juga dalil naqli yang berasal dari Hadis
yang merupakan ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah Saw. yang selamanya berada dalam bimbingan
Allah Swt.
b.
Dalil Aqli yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nash langsung, akan tetapi dengan
menggunakan akal pikiran manusia yaitu ijtihad.
Pendapat lainnya yang mengemukakan, bahwa sumber hukum islam berasal dari potensi-potensi sumber ilahi dan insani
atau dengan kata lain sumber naqliyah dan aqliyah. Dalil aqli yang
bersumber dari potensi insani dengan menggunakan akal pikirannya yang berupa
ijtihadi muncul apabila hukum tersebut tidak dapat ditemukan pada dalil naqli.
Oleh karenanya Allah dan Rasulnya memberikan kewenangan kepada potensi
insani yang berupa akal untuk menggali sehingga mampu menemukan serta
menetapkan hukumnya, namun tetap hal ini yang menjadi sandaran pokoknya adalah
Alquran dan hadis.
Dalil-dalil hukum
(sumber pengambilan hukum) terbagi kepada dua yaitu :
1) Dalil hukum Muttafa (disepakati) yaitu Alquran, Sunnah, ijma` dan qiyas.
2)
Dalil hukum Ghairu
Muttafa` (tidak disepakati) yaitu Istihsan,
Istishab, Maslahatul mursalah, saddu al-Zara`i.
·
Dalil hukum Muttafa` (disepakati) :
1. Alquran
Alquran menurut sebagian ahli, diantaranya al-Syafi`i
(150-204 H / 67-820 M), al-Farra` (207 H / 823 M), dan al-Asy`ari (206-324 H /
873-935 M), bahwa kata Alquran ditulis dan dibaca tanpa hamzah.36
Menurut al-Lihyani (w. 215 H/831 M) dan al-Zajjaj (w.
311 H / 298 M), bahwa kata Alquran sewazan
(sepadan) dengan fu`lan dan karenanya
harus dibaca dan ditulis ber-hamzah, meskipun dalam qira`at ada yang membacanya dengan Quran tanpa hamzah
itu semata-mata karena pertimbangan teknis yang lazim disebut dengan
mengalihkan harakat hamzah (fathah) kepada huruf yang sebelumnya (ra) yang sukun.
Seperti halnya perbedaan para pakar bahasa arab
mengenai tulisan dan bacaan Alquran,
mereka juga berbeda persepsi tentang asal-usul kata Alquran. Ada yang
mengatakan bahwa Alquran adalah ism `alam
(nama benda) yang tidak diambil dari kata apapun. Menurut as-Syafi`i kata
Alquran yang kemudian di ma`rifah-kan
dengan `alif lam tidak diambil dari
kata apapun, mengingat Alquran adalah nama khusus yang diberikan Allah Swt.
untuk nama Kitab yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad Saw. semisal Zabur bagi Nabi
Daud as., Taurat bagi Nabi Musa as., dan Injil bagi Nabi Isa as.37
36Muhammad Amin Suma, Studi Ilmu-Ilmu Alquran, jilid 1, cet.1,
(Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000) hlm. 18
37Pembahasan lebih jauh mengenai bacaan,
tulisan, dan asal-usul kata Alquran dapat dibaca dalam al-Suyuthi, al-Itqan fi `Ulum Alquran, jilid 1,
(Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, tt.), hal. 51, Manna al-
Pendapat lain, bahwa kata Quran yang kemudian di ma`rifat-kan dengan `alif lam itu adalah ism
musytaq (kata jadian) yang diambil dari kata lain, hanya saja, mereka
berlainan pendirian mengenai kepastian asl
kata Alquran tersebut. Ada pula yang mengatakan diambil dari kata qara`in jama` dari kata qarinah, yang berarti indikator, juga
ada yang menduga berasal dari kata qarana
dan al-qar`u / al-qaryu, yang masing-masing berarti
menggabungkan dan kumpulan / himpunan yang juga bermakna kampung (kumpulan
rumah-rumah).38
Para ahli ilmu-ilmu Alquran pada umumnya berasumsi
bahwa kata Quran berasal dari kata qara`a-yaqra`u-qira`atan-wa
qur`anan, yang secara harfiah berarti “bacaan”. Kata Quran sebanding dengan
kata fu`lan. Hal ini sesuai dengan
firman Allah Swat. Dalam surah al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi:
Artinya:
“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya
(di dadamu) dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai
membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu”.39
Arti Alquran secara terminologi ditemukan dalam
beberapa perumusan. Menurut Syaltut Alquran adalah lafaz Arabi yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad Saw. yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Menurut
Syaukani Alquran adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabu Muhammad Saw.
yang tertulis dalam bentuk mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Sedangkan
menurut Abu Zahrah Alquran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
Saw.40
Dengan menganalisa dan membandingkan defenisi yang
lain tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Alquran secara terminologi
ialah “Lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang
dinukilkan secara mutawatir”. Sedangkan menurut sebagian besar ulama Usul
fikih, Alquran adalah “kalam Allah Swt. yang memiliki mukjizat, diturunkan
kepada penutup para Nabi dan Rasul melalui perantara malaikat Jibril, yang
dinukilkan kepada generasi
Qaththan,
Mabahits fi `Ulum Alquran, (Riyadh :
Mansyurat al-`Ashar al-Hadis, 1393 H/1973 M.) hlm. 20 : Shubhi al-Shalih, Mabahits fi `Ulum Alquran,
(Beirut-Libanon: Dar al-`Ilm li al-Falayin, 1988) hlm. 18-19, dan Masyfuk
Zuhdi, Pengantar `Ulumul Qur`an,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1982) hlm.2
38Muhammad
Amin Suma, op.cit., hlm. 19
39Disebutkan
pula dalam Alquran (56) : 77 dan (69) ;36
40Ismail
Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam,
cet II, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm.
24
sesudahnya secara mutawatir, ditulis dalam masahif, membacanya merupakan
ibadah, dimulai dari surat al-Fatihah
dan ditutup dengan surat al-Nash”.41
Dari beberapa definisi Alquran tersebut, maka ia
mengandung beberapa unsur pokok yang menjelaskan hakikat dari Alquran itu :
1.
Alquran itu berbentuk lafaz yang mengandung
arti bahwa lafaz tersebut sampai
kepada kita sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Swt. melalui malaikat
Jibril, namun dilafazkan oleh Nabi
Saw. sendiri tidaklah disebut Alquran (seperti hadis Qudsi).
2.
Alquran itu berbahasa Arab yang berarti jika dialih
bahasakan ke dalam bahasa lainnya bukanlah Alquran.
3.
Alquran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang mengandung arti bahwa wahyu Allah Swt. yang
disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu tidaklah disebut Alquran.
Sebaliknya apa-apa yang dikisahkan dalam Alquran tentang kehidupan dan syari`at
yang berlaku bagi ummat terdahulu
adalah Alquran.42
4.
Alquran dinukilkan secara mutawatir yang mengandung arti bahwa ayat-ayat Alquran tidak
diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw. sekaligus berupa satu kesatuan mushaf, namun dinukilkan sesuai dengan
situasi dan kondisi tertentu.
Alquran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama
sekitar 23 tahun, dimana 13 tahun diturunkan di Makkah sebelum nabi Muhammad
Saw. hijrah ke Madinah dan 10 tahun
diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah
ke Madinah atau dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ciri-ciri khas
yang menonjol mengenai isi pada masing-masing tempat turunnya Alquran antara
lain :
1.
Ayat Makkiyah pada
umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyyah panjang-panjang
2.
Banyaknya surat Makkiyah
sekitar 19/30 dari isi Alquran, sedangkan surat Madaniyyah sekitar 11/30
dari isi Alquran.
41Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, jilid 1,
(Beirut : Dar al-Kutub al- Islamiyah,1983), hlm.82, Rachmat Syafe`i, Ilmu Ushul Fiqh, cet 1, ( Jakarta:
Pustaka setia, 1999), hlm. 50, dan Muhammad Amin Suma, op.cit., hlm. 24.
42Ismail Muhammad syah, op.cit.,
hlm. 24-26.
3.
Dalam surat Makkiyah
lazimnya terdapat perkataan “ya
ayyuhannas” dan sedikit sekali
terdapat perkatan “ya ayyuhalladzinaamanu”,
sedangkan dalam surat Madaniyyah malah sebaliknya.
4.
Ayat Makkiyah pada
umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan masalah keimanan, ancaman
dan pahala, kisah-kisah umat yang terdahulu
yang mengandung hukum-hukum, seperti hukum kemasyarakatan, hukum
ketatanegaraan, dan lainnya.43
5.
Alquran adalah syari`at Islam yang bersifat
menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari`at, karena
di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global yang perlu dijelaskan
dengan sunnah dan metode pengambilan istinbat hukum.
Menurut Ibnu Hazm bahwa setiap bab dalam fikih pasti
mempunyai landasan dalam Alquran yang dijelaskan oleh al-Sunnah.44 Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. QS.
(6) :38 yang artinya : “…. Tiadalah kami lupakan sesuatupun di dalam al-
Kitab…”.
Kandungan isi
Alquran sebagai sumber hukum antara lain :
1)
Ajaran-ajaran (konsepsi) mengenai kepercayaan (aqidah)
yang fokusnya adalah tauhid (monoteisme) dan sistem pengaturan hubungan antara khaliq (pencipta) dan makhluk (manusia).
2)
Berita (riwayat) tentang keadaan umat manusia sebelum
Nabi Muhammad Saw. menjadi Rasul, baik mengenai umat yang beriman dan yang tidak, beserta ganjaran hikmah yang didapatkannya.
3)
Berita yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada
masa mendatang, terutama pada kehidupan akhirat
4)
Peraturan-peraturan kemanusiaan, dalam hal ini adalah
hubungan interaksi selaku makhluk individu maupun sosial.
2.
Al-Sunnah
43Suparman
Usman, Hukum Islam, cet 1, (Jakarta :
Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 39
44Muhammad Abu Zahrah, Ushul
al-Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma`sum dkk., cet. VII ( Jakarta : Pustaka
Firdaus, t.th ), hlm.
Al-Sunnah adalah sumber pokok hukum islam kedua
setelah Alquran. Kata sunnah secara etimologi berarti “yang biasa dilakukan”.45
Sunnah dalam istilah ulama usul fikih adalah apa-apa yang diriwayatkan dari
nabi Muhammad Saw. baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan Nabi
Saw. yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan sunnah menurut ulama fikih adalah
sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut untuk dilakukan dengan pengertian
diberi pahala bagi orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang
meninggalkannya.46
Perbedaan ahli usul fikih dalam memberikan istilah
pada sunnah, sebagaimana disebutkan di atas karena perbedaan dalam segi sudut
pandang. Ulama usul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil
hukum syar`i. mereka mengatakan bahwa hukum itu ditetapkan dengan sunnah,
sedangkan ahli fikih menempatkan sunnah sebagai salah satu hukum syara` yang
lima. Mereka mengatakan bahwa perbuatan itu hukumnya sunnah, dalam pengertian
ini sunnah adalah hukum dan bukan dalil hukum.
Menjadikan sunnah sebagai sumber hukum sesuai dengan
firman Allah dalam Alquran (3) : 32 yang berbunyi :
ق اطيعلهللا والرسل فان تلللافإن هللا
اليحب الكفرين. kamu jika Rasulnya, dan Allah kepada sekalian kamu ta`atlah Katakanlah, Artinya:
berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak
menyukai orang-orang kafir.
Sunnah menurut
pengertian ahli usul terbagi menjadi tiga (3) macam :
1.
Sunnah
Qauliyah, yaitu ucapan
Rasulullah Saw. yang didengar oleh sahabat dan disampaikannya kepada orang lain. Contohnya, sahabat berkata bahwa
Rasulullah Saw. bersabda: “Menuntut ilmu itu
wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan”.
2.
Sunnah
Fi`liyah, yaitu perbuatan
yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. yang dilihat atau diketahui oleh sahabat
kemudian disampaikannya kepada orang lain. Contohnya,
sahabat berkata : “Saya melihat
Rasulullah Saw. melakukan salat sunnat dua rakaat sesudah salat zuhur”.
3.
Sunnah Taqririyah, yaitu perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapan atau
sepengetahuan Rasulullah Saw.. tetapi tidak dicegah oleh Rasulullah Saw.,
45Ismail
Muhammad syah, op.cit., hal.37
46Muin
Umar dkk., op.cit., hlm. 89 . Ismail
Muhammad Syah, loc.cit., hlm. 38
diamnya
Rasulullah Saw. tersebut disampaikan sahabat kepada yang lain. Misalnya seorang
sahabat memakan daging dab dihadapan Rasulullah Saw. sehingga Rasulullah Saw.
mengetahui apa yang di makan sahabatnya, tetapi Rasullullah Saw. tidak melarangnya.
Kisah tersebut disampaikan sahabat kepada lainya dengan ucapan : “Saya melihat seorang sahabat memakan dab di
dekat Nabi, Nabi mengetahui tetapi Nabi tidak melarangnya”.
Sunnah merupakan sumber kedua setelah Alquran,
karena Sunnah merupakan penjelasan dari
Alquran, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang
menjelaskan. Kedudukan Sunnah terhadap Alquran sekurang- kurangnya ada tiga hal
sebagaimana berikut :
1.
Sunnah sebagai ta`qid
(penguat) nash Alquran. Dalam hal
ini, Sunnah memberi ketegasan hukum sesuai dengan ketegasan nash Alquran,
sebagai contoh : Sunnah banyak yang menerangkan tentang kewajiban dan keutamaan puasa, shalat dan sebagainya.
2.
Sunnah sebagai bayanu
tasyri` (penjelas) nash Alquran.
Dalam hal ini sunnah berfungsi untuk menjelaskan secara praktis dari nash Alquran, sehingga menghindarkan
dari kekeliruan dalam mengklasifikasikan apa yang terkandung dalam Alquran.
Menurut Rachmat Syafe`I47, penjelasan Sunnah terhadap Alquran dapat
dikatagorikan menjadi empat bagian :
a.
Penjelasan terhadap hal yang global, seperti
diperintahkannya salat dalam Alquran tidak diiringi penjelasan mengenai rukun,
syarat, dan ketentuan lainnya. Maka hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Saw. : “Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu
telah melihat saya salat”.
b.
Penguat
secara mutlaq, Sunnah merupakan penguat terhadap dalil- dalil umum yang ada
dalam Alquran.
c.
Sunnah sebagai takhsis terhadap dalil-dalil Alquran
yang masih umum.
d.
Sebagai Musyarri` ( pembuat syari`at)
Dalam hal ini
terjadi perbedaan pendapat diantara ulama:
47Muin
Umar, dkk. Loc.cit., hlm.89
1)
Sunnah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam
Alquran
2)
Sunnah tidak memuat hal-hal yang tidak ada dalam
Alquran, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasanya dalam Alquran.
Ditinjau dari segi periwayatannya, maka sunnah dapat dibagi menjadi dua
macam yaitu:
1.
Sunnah yang bersambung mata rantai perawinya (muttasil al-Sunnah)
2.
Sunnah yang tidak bersambung mata rantai perawinya (ghairu muttasil al- sanad)
Sunnah yang bersambung mata rantai perawinya (muttashil al-sanad) jika dilihat dari
segi jumlah perawinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu :
1)
Sunnah
mutawatir ialah Sunnah yang diriwayatkan dari Rsulullah Saw. oleh sekelompok perawi yang menurut
kebiasaannya mereka tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Hal ini
disebabkan jumlah mereka yang banyak
dan diperoleh dari perawi yang terdahulu, yang sifatnya juga demikian sehingga
sampai sanadnya kepada Rasulullah Saw.
2) Sunnah Masyhur ialah sunnah yang diriwayatkan dari
Rasulullah Saw. oleh seseorang atau dua orang atau kelompok yang keadaannya
tidak sampai kepada tingkatan mutawatir yang
kemudian tersebar luas sehingga diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersepakat bohong.
Sunnah atau hadis masyhur menurut Abu
Hanifah menunjukkan ilmu yang pasti
(al-`Ilm al-Yaqin) walaupun
derajadnya masih dibawah Sunnah Mutawatir, dan menurut mazhab ini
pula, hadis masyhur dapat berfungsi
memperkuat ayat Alquran, sedangkan sebagian ahli fiqh menganggapnya sebagai
dasar yang zhan sebagaimana Hadis Ahad.
3)
Sunnah Ahad
atau khabar khassash menurut
Imam Syafi`I ialah setiap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. oleh
seorang atau dua orang yang belum
mencapai tingkatan syarat hadis masyhur.
48 Sunnah Ahad memberi
48Rachmat
Syafe`I, op.cit., hlm. 66-67
faidah ilmu yang pasti. Tentang kehujjahannya, para ulama berpendapat
bahwa Sunnah Ahad itu bisa dijadikan hujjah jika tidak ada dalil yang lain
yang lebih kuat, namun tidak dalam hal akidah, karena masalah akidah memerlukan
dasar yang pasti.
Adapun dengan sunnah yang tidak bersambung mata rantai
perawinya (ghair muttasil al-sanad)
kepada Rasulullah Saw. dinamakan oleh sebagian ulama dengan sebutan Sunnah/Hadis Mursal, sedangkan sebagian
ulama lain menamakannya Hadis Munqathi`,
dalam hal penggunaannya sebagai hujjah terjadi perbedaan pendapat. Imam Ahmad
tidak memakai hadis mursal ini
sebagai hujjah kecuali tidak
ditemukannya hadis lain pada kasus tersebut, Imam Syafi`I juga tidak memakainya
kecuali apabila tabi`in yang meriwayatkan hadis tersebiut telah tersohor dan
banyak bertemu dengan kalangan sahabat.
3. Ijma` (konsensus)
Ijma` adalah
kesepakatan para imam mujtahid dari umat Islam atas hukum syara` (mengenai
suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad Saw. wafat.49
Pengertian lain dari ijma` sebagaimana diungkapkan oleh Abdul
Wahhab Khallaf, yaitu : “Kesepakatan
seluruh Imam mujtahid dari kalangan kaum muslimin dalam salah satu kurun dari
kurun-kurun yang banyak sesudah wafat Rasulullah Saw. terhadap suatu peristiwa
hukum syara`”.50
Adapun Ibnu Taimiyyah memberi batasan pengertian ijma`
sebagaimana berikut: “Makna Ijma` adalah
kesepakatan ulama kaum muslimin mengenai suatu hukum dari beberapa hukum”.51
Ijma` merupakn
sumber yang kuat dan merupakan salah satu metode pengembangan ijtihad untuk
meneruskan dan menerapkan hukum-hukum Islam. Jika sudah terjadi kemufakatan
atas suatu hukum, maka sudah barang tentu ada dalil (alasan) yang menjadi
sandarannya, sebab tidak masuk akal kalau para ulama bersepakat atas sesuatu
hukum tanpa mempunyai dalil syara`. Hal ini sesuai dengan
hlm. 234
49Ibid..
50Muhammad
Salam Madkur, Al-Madkhal lil Fiqh
al-Islamy, (Cairo : Dar al-Nahdah, 1960),
51Dahlan Idhamy,
Karakteristik Hukum Islam,
(Surabaya: al-Ikhlas, 1985)
hlm. 84. Adbul
Wahhab Khallaf, Op.cit.,
hlm. 45
hadis
Rasulullah Saw. : “Ummatku tidak akan
bersepakat untuk melakukan kesalahan”. (H.R. Abu Daud dan al-Turmudji).52
Alasan menempatkan ijma` sebagai dasar hukum setelah Alquran
dan Sunnah juga dikuatkan oleh beberapa Asar
sahabat Nabi Muhammad Saw. diantaranya sebagaimana disampaikan Umar ibn
al-Khattab kepada Syuraih : “ Putuskanlah
(perkara itu) menurut hukum yang ada dalam kitab Allah, kalau tidak ada (dalam
Alquran), maka putuskanlah sesuai dengan hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah
Saw. kalau tidak ada (dalam sunnah Rasulullah Saw.) putuskanlah berdasarkan hukum
yang telah disepakati oleh (ummat) manusia”.
Dalam
riwayat lain : “Putuskanlah menurut hukum
yang telah ditetapkan oleh orang- orang saleh”.
Dasar lain, sebagaimana yang dikatakan Ibn Mas`ud : “Siapa yang ditanya
tentang (hukum) suatu masalah seyogyanya ia memberikan fatwa berdasarkan hukum
yang ada dalam kitab Allah, Kalau tidak ada (dalam Alquran), maka berfatwalah
menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan kalau tidak ada (dalam
Hadis), hendaklah berfatwa menurut hukum yang telah disepakati oleh umat
manusia (umat Islam).53
Objek ijma` ialah
semua peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan dasarnya dalam Alquran dan
Sunnah atau peristiwa yang berhubungan
dengan ibadah ghairu mahdah (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Swt.)
bidang muamalah, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan
dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Alquran dan Hadis.54
Ijma` ditinjau
dari cara terjadinya, menurut ahli Ushul Fiqh dibagi menjadi dua, yaitu Ijma` Bayani (disebut juga Ijma` Qauli, Ijma` Sharih atau Ijma` Haqiqi) yaitu kemufakatan yang
dinyatakan atau diucapkan oleh mujtahidin, termasuk dalam katagori ini tulisan
mujtahidin yang diakui oleh para mujtahidin lainnya. Yang kedua Ijma` Sukuti disebut juga dengan Ijma` I`tibari, yaitu kebulatan yang
dianggap ada
52Muhammad Amin Suma, Ijtihad
Ibnu Taimiyah dalam Fiqh Islam, cet II, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002),
hlm. 118.
53Muin
Umar,dkk, Op.cit., hlm. 100
54Muhammad
Amin Suma, op.cit., hlm. 117
apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh
mujtahid lainnya, akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau
bantahannya.55
Sedangkan Abdu al-Rahman dalam bukunya Shari`ah The Islamic menambahkan
pembagian tersebut dengan Ijma` Fi`li,
yaitu kesepakatan para mujtahid dengan melakukan tindakan yang tidak dinyatakan
bantahan atau persetujuan terhadap tindakan tersebut.56
Adapun
kriteria Ijma` menurut sebagian ulama
ushul adalah :
1)
Kesepakatan sekelompok fuqaha /ulama
2)
Pada kurun waktu tertentu
3)
Di ruang lingkup suatu wilayah atau kawasan tertentu pula.
Dengan
penjelasan di atas, maka sebenarnya Ijma`
sangat efektif untuk :
1)
Menjadi asas Ijtihad Jama`I (Ijtihad kolektif)
2)
Melandasi penemuan serta pengembangan hukum
kontekstual menurut kondisi ruang dan waktu. Dari sini lebih jelas tampak bahwa
hukum Islam memiliki sifat kelenturan (elastisitas dan Fleksibelitas).
4. Qiyas (Analogi)
I.
Pengertian Qiyas
Kata qiyas
merupakan derivasi (bentukan) dari “ يقااي - قااا" , artinya mengukur.57 Secara etimologi, term al-qiyas mengandung beberapa makna, dan yang
terpenting ialah makna “persamaan”
(al-musawah) dan “pengukuran”
(al- taqdir). Makna “persamaan” itu dalam arti mutlak, baik
yang bersifat indrawi,
misalnya, ungkapan “qasa al-tsaub bi al-tsaub”( pakaian ini menyamai pakaian itu) dan ungkapan “qistu al-burtuqalah bi al-burtuqalah” ( saya menyamakan jeruk ini dengan jeruk itu). Sedangkan makna persamaan yang bersifat non indrawi
terlihat pada ungkapan “fulan
yuqasu bi fulan” (si fulan tidak disamakan dengan si fulan). Sedangkan makna pengukuran (al-taqdir)
terdapat pada ungkapan “qasa al-tsaub bi
55Ibid., hlm. 118
56Muin
Umar, dkk. Op.cit., hlm. 106.
57Louis
Ma`luf, al-Munjid fi al-Lugah,
(Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 665.
al-mitr” ( dia mengukur pakaian itu dengan alat meteran), dan ungkapan “qasa al- ard bi al-qasbah” ( dia mengukur tanah itu dengan bambu).
58
Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai
rumusan yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, berbagai rumusan definisi
qiyas yang mereka kemukakan dapat dikategorisasikan sebagai berikut :
حكمه علة فى ألص فرع مساوة Artinya: Persamaan far`u dengan asl dalam hal `illat hukumnya.59
حم معللم
على معللم فى إثبات حكوم لهموا أو نفيوه عنهموا بوأمر جوامم بينهموا مون إثبوات حكوم أو
صوفة أونفيهموا
عنهما60.
Artinya: Menghubungkan
sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal
ada atau tidak adanya hukum
berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa penetapan maupun peniadaan
hukum /sifat dari keduanya.
Menurut Abu Zahrah,
qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nas hukumnya kepada perkara baru yang ada nas hukumnya karena keduanya
berserikat dalam ‘illat hukum.
Sedangkan menurut Ibnu Qudamah
qiyas adalah:
حم فرع على أص فى حكم بجامم بينهما
Artinya: Menghubungkan
furu’ kepada asl dalam hukum karena
ada hal yang sama (yang menyatukan)
antara keduanya.61
Para ahli usul menyatakan
bahwa qiyas adalah menerangkan hukum
sesuatu yang tidak ada nasnya baik dalam Alquran maupun hadis dengan cara
membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.62
Dapat dipahami secara tidak langsung bahwa qiyas
adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan nas (Alquran dan hadis)
kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena serupa makna hukum yang
disebutkan.
58Ibnu Manzhur, Lisan al-`Arab, (Beirut: Dar al-Shadir, tt.) juz ke-8, hlm. 70.
Lihat juga Abu Zakariyya Syaraf al-Nawawi, Tahdzib
al-Asma` wa al-Lugah, ( Beirut: Dar al-Tiba`ah al-Muniriyyah, tt.) juz
ke-9, hlm. 225
59Ibnu al-Hajib, Mukhtasar Ibnu al-Hajib, ( Kairo : Maktabah al-Kulliyyat
al-Azhariyyah,1993), Juz 2, hlm. 205.
60Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min `ilm al-Usul, (beirut :
Dar al-Ihya`, 1990), Juz 2, hlm. 254. Lihat juga Fakhruddin al-Razi, al- Mahsul fi `Ilm al-Usul, (Beirut :
Dar al-Fikr, 1990), Juz 2, hlm. 2. Lihat Dr. Asmawi, M.Ag., Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta :
Amzah,2013) hlm. 94.
hlm.22
61Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 147.
62Abd
al-Wahhab al-Khallaf, Masadir al-Tasyri`
al-Islamiy, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1982),
Dengan demikian, ketetapan
hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dapat
dikatagorikan sebagai qiyas, dengan dalil harus memenuhi keempat rukunnya.
II.
Rukun Qiyas
Rukun qiyas terdiri dari empat unsur, yaitu:
1.
AL-Asl (pokok) yaitu sumber hukum yang terdiri dari nas yang menjelaskan tentang hukum, sebagian besar ulama menyebutkan
bahwa, sumber hukum yang dipergunakan sebagai dasar qiyas harus berupa nas, baik nas Alquran,
hadis maupun ijma`, dan tidak boleh mengqiyaskan
sesuatu dengan hukum yang ditetapkan dengan qiyas.63 Asl disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi ukuran), Mahmul `alaih atau musyabbah
bih (tempat menyamakan).
2.
Al-Far`u (cabang) yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan nasnya.
Artinya, kasus yang ada
tidak diketahui hukumnya secara pasti. Al-Syafi`i, dalam hal
ini mengatakan, bahwa far`
itu adalah suatu kasus yang tidak disebutkan hukumnya secara tegas dan diqiyaskan kepada hukum aslnya.64 Al-Far’u disebut juga maqis (yang diukur), mahmul atau musyabbah (yang diserupakan).
3.
Al-Hukm, yaitu hukum yang terdapat
pada asl. Hukum disini adalah
hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya,
baik secara tegas maupun ma`nawi. Ini berarti, hukumnya
harus berdasarkan Alquran dan
Hadis, harus dapat dicerna akal
tentang tujuannya dan hukum yang ditetapkan
bukan masalah rukhsah dan khusus.
4. ‘Illat, secara bahasa dapat berarti al-maradh,
yaitu penyakit, atau al-sabab,
yaitu sebab yang melahirkan atau menyebabkan
adanya sesuatu Dalam konteks qiyas,
63Sya`ban Muhammad Isma`il, op.cit., hlm.205. Lihat juga Muhammad
Abu Zahrah, Usul al- Fiqh, alih
bahasa oleh Saefullah Ma`sum, dkk, (Jakarta : P3M,1994), hlm. 353. Lihat juga
al-Syafi`I, al- Risalah, (Mesir : Dar
al-Saqafah, 1973), hlm.25.
64Al-Syafi`i, Ibid.,
hlm.43
maka pengertianya yang kedua, yaitu “sebab” adalah lebih sesuai,
karena `illat tersebut menyebabkan tetapnya hukum pada far`u yang
dituntut untuk menetapkan hukumnya.65
Al-Juwayni mendefenisikan Illat sebagai berikut :
والعلة هى الجالبة للحكم بمناسبتها له. 66
Artinya: `Illat
itu adalah sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum karena keserasiannya
bagi ketentuan hukum tersebut.
Menurut al-Ghazali,
bahwa `illat itu adalah sifat yang
berpengaruh terhadap adanya hukum
dengan sebab ditetapkan Allah, sedangkan
menurut al-Syafi`i, `illat
itu wasf yang zahir, mundabit
dan mu`arrif . hukum furu` sama
dengan hukum pada asl. Artinya, bahwa
`illat itu harus dapat dicerna oleh panca indra dan harus nyata. Bilamana sifat ini ditemukan pada furu`, status hukum yang terdapat
pada asl menjadi berlaku pula pada furu. Inilah maksud dari ungkapan : al-hukm yaduru ma`a
`illatihi wujud-an
wa
`adam-an (keberadaan hukum
itu mengikuti keberadaan
`illat).67
Untuk lebih jelasnya pemahaman terhadap masing-masing rukun qiyas tersebut dikemukakan contoh sebagai berikut: Bagaimana hukum menjual harta
anak yatim. Nasnya tidak ada; yang ada makan harta
anak yatim. Jadi hukumnya haram berdasarkan Surah an-Nisa` ayat 10.
1.
Makan harta anak yatim disebut
asl.
2.
Menjual harta anak yatim
disebut furu’.
3.
Haram makan harta anak yatim disebut
hukum asl.
4.
Makan harta anak yatim
itu sifatnya mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim,
disebut ‘illat.
65`Abd
al-Hakim `Abd al-Rahman As`ad al-Sa`di, Mabahits
al-`Illat fi al-Qiyas `ind al-Usuliyin
(Beirut : Dar al-Basya`ir al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), hlm.
68-69.
66Al-Juwayni, al-Waraqat
fi al-Usul pada margin Irsyad
al-Fuhul ila al-Syawkani (Beirut : Dar al-Fiqh, tt.) hlm. 212
67Abu
Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa
min `Ilm al-Usul, Juz 2, hlm. 325
Menjual harta
anak yatim sifatnya juga mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim tersebut. Berarti menjual harta anak yatim sama sifatnya
(‘illatnya) dengan makan harta anak yatim. Dengan demikian menjual harta anak yatim hukumnya haram
menurut Qiyas”. 68
Alquran dan
hadis secara eksplisit tidak pernah membicarakan
qiyas, namun sebagaimana diketahui, bahwa keduanya adalah sumber hukum utama yang
sifatnya terbatas dan hanya memuat kansep-konsep umum dalam rangka menjawab setiap persoalan yang muncul. Keduanya
memberi peluang bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dengan qiyas.
Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa` (4:59)
yang berbunyi :
يايها الذين امنوا اطيعوا هللا واطيعوا الرسول واولى األمر منكم فان تنازعتم في شيئ فردوه الى هللا
.تأويال واحسن خير ذلك
األخر
واليوم باهلل تؤمنون كنتم ان
والرسول Artinya: Hai
orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan pemimpin-pemimpin diantara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur`an) dan Rasul (al-
Hadis) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang
demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Kata-kata
"
والرسول هللا الى فردوه "
mengandung arti, mengembalikan semua peristiwa yang muncul kepada Alqur`an
dan hadis meliputi berbagai cara, termasuk dengan menghubungkan suatu peristiwa
yang tidak ada nas hukumnya karena ada kesamaan `illat. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Alquran maupun hadis
telah menjawab segala persoalan yang muncul baik secara tekstual maupun isyarat.69
Disamping itu, hadis juga menggambarkan praktek qiyas melalui ijtihad. Seperti peristiwa Muaz bin Jabal ketika diutus Rasul ke
Yaman. Sebagaimana disebutkan, salah satu landasan menetapkan hukum disamping
Alquran dan hadis adalah ijtihad,
termasuk menganalogikan peristiwa yang tidak ada nasnya kepada yang ada nasnya
dengan persamaan `illat70.
G.
Dalil hukum Ghairu Muttafa` (tidak disepakati)
68Kamal
Mukhtar, dkk., jilid I, op.cit., hlm.
118-119
69Abd
al-Wahhab Khallaf, op.cit., hlm.31
70Ibid., hlm.32
a.
Istihsan
Sebelum lebih
lanjut membicarakan istihsan, perlu
diutarakan pengertian metode ijtihad.
Metode ijtihad adalah jalan
yang ditempuh seseorang mujtahid dalam memahami, merencanakan dan merumuskan suatu hukum syara’ amaly. Ada beberapa macam metode ijtihad sebagai
hasil rumusan mujtahidin. Ada metode ijtihad
yang merupakan ciri khas seseorang mujtahid yang tidak
digunakan oleh mujtahidin lainnya, sehingga
berimplikasi munculnya perbedaan
hasil ijtihad antara seorang mujtahid
dengan mujtahid lainnya.
Metode ijtihad lazim
digunakan dan dipandang sebagai metode ijtihad
yang paling tinggi kualitasnya dan digunakan hampir semua ulama fikih
adalah qiyas. Metode-metode ijtihad itu cukup banyak, yaitu istihsan, maslahat mursalah, istishab,
‘ urf, saddu al-zari’ah, qaul al-sahabi dan syar’u man qablana.71
Istihsan menurut lughawi berarti memperhitungkan
sesuatu lebih baik atau mencari
yang lebih baik untuk diikuti. Secara istilah, istihsan menurut pendapat Ibnu Subki adalah beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih
kuat dari padanya. Menurut
pendapat asy-Satibi dari Malikiyyah adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz`i sebagai pengganti yang bersifat
kulli. Sedangkan Ibn Qudamah dari Hanabilah menyatakan, “sesuatu yang dianggap
lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan
pendapat akal”. Al-Ghazali mengatakan “semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya.72
Dilihat dari
sisi dalil yang digunakan, istihsan terbagi
tiga macam, yaitu:
1.
Beralih dari qiyas jali kepada qiyas khafi karena dipandang lebih tepat. Contoh: mewakafkan sebidang tanah yang di dalamnya ada jalan dan sumber air, apakah dengan semata mewakafkan sebidang tanah tersebut termasuk jalan dan sumber airnya?
Menurut qiyas jali disamakan dengan akad jual beli,
berarti tidak termasuk jalan dan sumber air. Namun lebih tepat disamakan dengan sewa-
71Amir
Syarifuddin, Ushul Fiqh I, Cet. I,
(Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 303-304.
72Rahmat Syafe`I, Ilmu
Ushul Fiqih, ( Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm. 111, Amir Syarifuddin, op.cit., hlm. 305-306
menyewa (qiyas khafi, karena
persamaan ‘illatnya lemah) sehingga
jalan dan sumber air termasuk dalam akad.
2.
Beralih dari
pengertian umum yang dituntut
suatu nas kepada hukum yang bersifat khusus. Contoh: sanksi hukum
terhadap pencuri. Menurut nas (surah al- Maidah ayat 37), sanksi hukumnya adalah potong tangan. Namun bila
pencurian itu dilakukan pada musim kelaparan, maka tidak dikenakan hukum
potong tangan.
3. Beralih dari hukum yang bersifat umum kepada hukum pengecualian. Contoh: Islam melarang memperjualbelikan
sesuatu yang tidak dilihat. Namun berdasarkan istihsan dibolehkan seperti
jual beli saham, muzara’ah dan lain- lain.73
Ulama-ulama Hanafiyah mengakui istihsan
sebagaimana Abu Hanifah
banyak menggunakan istihsan. Ulama-ulama Malikiyah berpendapat
bahwa istihsan adalah dalil yang kuat sebagaimana
Imam Malik banyak berfatwa menggunakan istihsan.74 Tetapi al-Jalal
dan al-Mahalli menyatakan bahwa istihsan diakui oleh Abu
Hanifah, tetapi ulama-ulama lain mengingkarinya termasuk
golongan Hanabilah. Adapun ulama-ulama Syafi’iyah telah masyhur tidak
mengakui istihsan, dan tidak menggunakannya sebagai dalil.
Bahkan Imam Syafi’i berkata: “barang siapa menggunakan istihsan
berarti ia telah membuat syariat”75
b. Istishab
Istishab menurut etimologi
berarti “selalu menemani”; selamanya
menyertai. Menurut terminologi
istishab adalah “mengukuhkan apa yang pernah
ada” (definisi ini dikemukakan oleh Mhd. Rida Muzaffan dari kalangan Syi’ah). Menurut
asy- Syaukani istishab adalah “apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa
lalu, pada
73M.Asywadie
Syukur, op.cit, hlm. 114.
74Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa asy-Syatibi, al_Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, jilid IV,
(t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 15.
75Abd
al-Wahhab Khallaf, op.cit., hlm. 83.
prinsipnya tetap berlaku pada masa akan datang”.76 Sedangkan
menurut asy-Syatibi, istishab adalah
“segala keputusan yang telah ditetapkan pada masa lalu, hukumnya tetap berlaku
pada masa sekarang.”77
Ulama Hanafiyah menyatakan sebenarnya istishab itu hanyalah untuk
mempertahankan berlakunya hukum yang telah ada, bukan menetapkan hukum yang
baru. Dengan demikian istishab dapat
dijadikan dasar hujjah sebagaimana
digunakan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali dan
Zahiri.
Menurut Ibn
qayyim istishab terbagi tiga bentuk,
yaitu:
1.
Istishab
al-bara`ah al-asliyah, berarti bersih atau
bebas dari beban hukum yakni pada
dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada petunjuk berlakunya beban hukum kepada yang bersangkutan.
2.
Istishab
al-sifat, yakni mengukuhkan
berlakunya hukum pada suatu sifat baik
memerintahkan maupun melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan
yang mengakibatkan berubahnya hukum.
3.
Istishab
hukmi al-ijma’, yakni mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan
berdasarkan ijma’.78
Contoh-contoh
hukum berdasarkan istishab:
1)
Seorang laki-laki “A” beristri
“B”, kemudian berpisah tempat cukup lama.
Karena cukup
lama, “B” ingin kawin dengan “C”. Berdasarkan istishab, “B” masih tetap istri “A”, dan “B” tidak boleh kawin
dengan “C”.
2)
Seseorang yang telah
berwudu’, wudu’nya tetap berlaku
sampai dia yakin telah batal.
3)
Pemilikan harta bagi
seseorang tetap berlaku
selama tidak ada bukti kepemilikannya telah beralih
kepada orang lain.
76Muhammad
Abu Zahrah, op.cit., hlm. 342 77Mukhtar
Kamal, dkk., jilid 1, op.cit., hlm.
152. 78Amir Syarifuddin, op.cit.,
hlm. 347-348.
4)
Dihalalkan bagi manusia makan
apa saja yang ada di muka bumi
ini (surah al-Baqarah ayat 29), kecuali ada dalil yang mengatakan
haram. Maka berdasarkan istishab, kita boleh makan apa saja kecuali ada dalil yang mengatakan
tidak halal dimakan.
c.
Maslahat Mursalah
Maslahat
mursalah secara lughawi berarti
manfaat atau kebaikan yang tidak ada nasnya.
Maslahat mursalah secara istilah
adalah:
1.
Menurut asy-Syaukani: maslahat yang tidak diketahui apakah syara’
menolaknya atau memperhatikannya.
2.
Menurut Ibn Qudamah:
maslahat yang tidak ada petunjuk tertentu membatalkanya dan memperhatikanya.
3.
Menurut Abdul
Wahab Khallaf: maslahat yang tidak ada dalil syara’ untuk mengakuinya atau menolaknya (Syarifuddin, 1997:333-334).
4.
Menurut Ibn Taimiyyah
dalam artikelnya yang dikutip
Muhammad Abu Zahrah
79 “sesuatu yang dipandang oleh mujtahid sebagai perbuatan yang sarat dengan manfaat dan tidak ada ketentuan syara’ yang menafikannya.
Imam Malik dan pengikutnya menggunakan maslahat
mursalah sebagai metode ijtihad. Sebagian ulama
Hanafiyah dan Syafi’iyah juga menggunakan maslahat mursalah (penjelasan Ibn
Qudammah dari Hanabilah).
Sementara al- Ghazali sebagai
pengikut Imam Syafi’i menyatakan
bahwa ia menerima penggunaan maslahat mursalah dengan syarat menyangkut
kebutuhan pokok dalam kehidupan dan menyeluruh secara kumulatif. Sedang
menurut para ulama Hanabilah, maslahat mursalah tidak memiliki kekuatan hujjah dan tidak boleh
melakukan ijtihad melalui metode ini.
Dapat dilihat bahwa dalam penggunaan maslahat
mursalah ada yang pro dan ada yang kontra.
Menurut al-Amidi kelompok yang menolak adalah golongan
79Muhammad
Abu Zahrah, op.cit., hlm. 495
mayoritas (jumhur). Perlu ditegaskan bahwa
lapangan maslahat mursalah adalah mu’amalah
dan adat. Ada beberapa argumentasi para ulama
yang menggunakan maslahat mursalah antara lain:
1. Ada
persetujuan Rasulullah menurut penjelasan
Mu’az bin Jabal, boleh
menggunakan ra`yu (daya nalar) bila
tidak menemukan ayat-ayat Alquran dan Sunnah dalam menyelesaikan
kasus hukum.
2.
Telah cukup meluas di kalangan
sahabat tentang penggunaan maslahat
mursalah, seperti pencetakan mata uang pada masa Umar bin Khattab; penyatuan qira`ah Alquran zaman Usman; memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat masa Abu Bakar;
dan diberlakukannya azan dua kali pada
zaman Usman.
3.
Apabila maslahat sesuatu sudah cukup nyata dan sesuai dengan maksud hukum syara’ maka menggunakan maslahat mursalah berarti memenuhi tujuan syara’. Sebaliknya bila tidak digunakan berarti melalaikan
tujuan hukum syara’.
4. Bila tidak boleh menggunakan maslahat mursalah sebagai metode ijtihad, dalam masalah tertentu
akan menjadikan umat dalam kesulitan, padahal Allah menghendaki
kemudahan bagi hamba-Nya.
Ulama-ulama yang menolak maslahat mursalah sebagai metode ijtihad,
mengemukakan beberapa alasan, antara
lain:
1.
Sesuatu yang tidak
ada petunjuk syara’ membenarkannya berarti bukan suatu maslahat. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk
syara’ berarti mengakui kurang lengkapnya Alquran dan
Sunnah, padahal Alquran dan Sunnah sudah lengkap meliputi semua hal.
2. Mengamalkan
sesuatu yang tidak
memperoleh pengakuan tersendiri dari nas
berarti menuruti kehendak hati
dan kemauan hawa nafsu.
3.
Menggunakan maslahat
dalam ijtihad tanpa nas berarti
bebas
menetapkan hukum, hal ini dilarang
dalam Islam.
4.
Bila dibolehkan berijtihad dengan
maslahat yang tidak mendapat dukungan
dari nas, besar kemungkinan terjadi perubahan hukum syara’ karena perubahan waktu dan tempat, atau karena berlainan tinjauan
seseorang dengan orang lain, sehingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan
prinsip hukum syara’ yang bersifat universal dan meliputi semua umat Islam.
d. Saddu al-Zari’ah
Saddu berarti
penghalang, penghambat, penutup. Zari’ah berarti jalan. Saddu zari’ah berarti
penghalang atau penutup jalan.80 Menurut Ibn Qayyim, istilah
al- zari’ah diartikan dengan
“apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”. Menurut Badran al-zari’ah adalah “sesuatu yang menyampaikan
kepada yang terlarang yang mengandung kerusakan.”81
Perlu dikemukakan bahwa menurut Ibn Qayyim, zari’ah itu ada dua macam, yaitu
bertujuan kepada yang dilarang dan bertujuan kepada yang dianjurkan. Yang
bertujuan kepada yang dianjurkan disebut fathu
al-zari’ah.82
Para ulama usul fikih membagi zari’ah dari dua sudut tinjauan:
1.
Dilihat dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya,
terbagi empat macam, yaitu:
a. Membawa kepada kerusakan secara pasti. Misalnya: menggali lobang dekat tangga dapat, dipastikan pemilik rumah akan jatuh ke dalamnya.
b.
Kemungkinan besar menimbulkan kerusakan. Contoh: menjual anggur ke pabrik pengolahan minuman keras.
80Kamal
Mukhtar, dkk., op.cit., hlm. 156.
81Amir
Syarifuddin, op.cit., hlm. 399.
82Nasrun
Haroen, op.cit., hlm. 160-161
c.
Menurut kebiasaan akan
menimbulkan kerusakan. Contoh: menjual senjata
kepada musuh. Jual beli secara kredit, biasanya menimbulkan riba.
d. Belum tentu menimbulkan kerusakan tetapi dapat menimbulkan kerusakan.
Contoh: menggali
lobang di kebun (jarang dilalui orang) mungkin juga ada orang yang jatuh di
dalamnya
2.
Dilihat dari sudut dampak kerusakan yang ditimbulkannya menurut Ibn Qayyim terbagi dua:
a. Perbuatan
itu pada dasarnya mengakibatkan kerusakan.
Contoh: meminum minuman keras.
b. Perbuatan itu pada dasarnya boleh, tetapi dijadikan melakukan
yang haram.
Contoh: menikahi wanita yang ditalak tiga suamianya, tujuannya supaya
bisa nikah lagi dengan suami pertama (hukumnya haram).83
Saddu al-Zari’ah
menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah
dapat diterima sebagai dalil hukum,
sedang ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah dapat menerimanya dalam masalah-masalah
tertentu saja. Seperti, sakit dan musafir boleh meninggalkan shalat Jum’at dan menggantinya dengan
shalat zhuhur, tetapi harus secara sembunyi supaya
tidak muncul fitnah. Begitu juga boleh tidak puasa karena sakit, tetapi jangan makan/minum di depan orang banyak. Ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menerima saddu al-zari’ah sebagai
dalil hukum, bila kerusakan
diyakini pasti terjadi atau diduga
keras terjadi.84
BAB III
IJTIHAD, ITTIBA` DAN TAQLID
1. IJTIHAD
A.
Pengertian dan Dasar Hukum Ijtihad
83Nasrun
Haroen, op.cit., hlm. 162-166.
84Amir
Syarifuddin, op.cit., hlm. 167-169
Berdasarkan sejarah,
istilah ijtihad pada mulanya dipergunakan
untuk mengungkapkan sebuah upaya penalaran
dan pemikiran yang mendalam
tentang suatu persoalan yang membutuhkan
pemecahan hukum. Ijtihad masih dipahami
sebatas pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli
serta belum terdefinisikan dan terumuskan dalam metode-metode tertentu.
Secara etimologis berarti bersungguh-sungguh atau
berusaha keras.85 Kata ijtihad
dalam sintaksis Arab mengikuti wazan
ifti’al yang menunjukkan arti mubalagah dalam suatu tindakan atau
perbuatan.86 Sedangkan pengertian terminologisnya, ada beberapa
rumusan yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:
1.
Menurut Imam asy-Syaukani
(1349 H : 250)
بذ اللسم فى ني حكم شرعى عملى بطريق االستنباط
Artinya : Mengerahkan kemampuan
dalam memperoleh hukum syar’i yang bersifat amali melalui cara istinbat.
2.
Menurut Imam al-Ghazali87
“usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid
untuk mengetahui hukum-hukum
syariat”.88
3.
Menurut kebanyakan
ahli usul: “pencurahan kemampuan secara
maksimal untuk mendapatkan sesuatu
hukum syara’ yang sifatnya zanniy89 Adapun
dasar hukum ijtihad cukup banyak, baik berdasarkan
ayat-ayat Alquran maupun Sunnah dan juga dalil
aqli. Di antara ayat-ayat Alquran yang
menunjukkan/menyuruh ijtihad adalah surah an-Nisa ayat
105. Maknanya: “sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab
dengan benar agar
85Ibn
Manzur, Lisan al-Arab, Jilid III,
(Beirut : Dar as-Sadr, t.t.) hlm. 103.
86Yusuf al-Qardhawi, al-Ijtihad
fi asy-Syariah al-Islamiyyah ma`a Nazarat Tahliliyyah fi al- Ijtihad al
Mu`asir, terj. Ahmad Syathari, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) hlm. 1.
87Kamal Mukhtar, dkk., jilid 1, op.cit., hlm. 116
88Imam Zaid juga memberikan definisi
yang hampir sama. Lihat: Muhammad Abu Zahrah,
Abu Hanifah : Hayatuh wa `Asruh
`Ara`uh wa Fiqhuh,
( Kairo : Dar al-Fikr al-`Araby, 1952) hlm. 453
89Tim Penyusun Text Book, Pengantar
Ilmu Fiqh, (Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat,
1981) hlm. 136
engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan
oleh Allah kepadamu”.
Di antara Sunnah yang menunjukkan
boleh berijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra. Maknanya: jika seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihadnya
dan benar maka dia mendapat
dua pahala dan bila salah
maka ia mendapat satu pahala. 90
Dari segi dalil aqli dikemukakan sebagai berikut:
Kehidupan umat manusia tambah
maju dan semakin kompleks, sehingga muncul berbagai kasus
baru, sedang penetapan hukumnya tidak
ditemukan secara tegas dalam Alquran maupun
dalam Hadis. Apabila ijtihad tidak diperbolehkan
tentu terlalu banyak kasus yang tidak mendapat penyelesaian
hukum dan kita yakin bahwa syariat
Islam tidak membolehkan penganutnya mendiamkan kasus-kasus tersebut.91
B.
Kedudukan dan Fungsi Ijtihad
Ijtihad dilakukan apabila menghadapi suatu masalah yang memerlukan
penetapan hukum syara’ sedang
pada ayat-ayat Alquran dan Hadis tidak ditemukan secara tegas
penetapan hukumnya, begitu juga
ijma’ sahabat belum ada yang
membicarakannya.
Ulama-ulama yang boleh bahkan wajib melakukan ijtihad adalah yang sudah ahli, seperti
pada zaman mujtahid yang empat.
Pendapat-pendapat yang mereka kemukakan baik berupa qiyas, termasuk ijtihad.
Begitu juga pendapat-pendapat yang tidak termasuk dalam qiyas seperti istihsan yang
digunakan oleh Imam Hanafi atau maslahat
mursalah oleh Imam Maliki dan pengikutnya termasuk ijtihad. Para Imam mujtahid melakukan
ijtihad dalam rangka menuntun umat
berada dalam batas-batas yang ditetapkan hukum syara’.
Dapat disimpulkan bahwa ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat
Islam. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa ijtihad
berfungsi melahirkan ketenteraman bagi umat karena masalah yang mereka
hadapi mendapat penyelesaian berdasarkan ijtihad
tersebut.92
C.
Objek dan Macam-macam Ijtihad
90Rahmat
Syafe`I, op.cit., hlm. 102
91Tim
Penyusun Text Book, op. cit., hlm.
138
92Kamal
Mukhtar, dkk., Jilid I, op.cit., hlm.
122
Objek ijtihad adalah masalah hukum syara’ yang
tidak memiliki dalil yang
qat’iy. Apabila ada nas yang keberadaannya zanniy seperti hadis ahad maka
yang menjadi lapangan ijtihad dalam hal ini adalah
meneliti bagaimana sanadnya, derajat para perawinya dan lain-lain. Manakala ada nas yang petunjuknya zanniy, maka yang menjadi lapangan
ijtihad adalah bagaimana
maksud nas tersebut dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, kaidah ‘am,
khas dan lain-lain. Berkenaan dengan masalah
syara’ yang tidak ada nasnya,
maka yang menjadi lapangan ijtihad adalah seluk-beluk
masalah tersebut secara keseluruhan.93
Dilihat dari
segi dalil yang dibuat sebagai pedoman, ijtihad
terbagi tiga macam, yaitu:
a.
Ijtihad bayani; yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung
dalam nas yang petunjuknya zanniy. Ijtihad dalam hal ini memberikan bayan (penjelasan)
yang positif dari dalil nas
tersebut. Contoh: pengertian tiga quru’
pada surah al-Baqarah ayat 228; bisa berarti tiga kali suci,
bisa
berarti tiga kali haid. Imam Syafi’i
berijtihad mengambil pengertian tiga kali suci, sedang Imam Hanafi mengambil pengertian tiga kali haid.
b. Ijtihad qiyasi, yaitu menetapkan hukum
suatu peristiwa berdasarkan
qiyas/menurut
metode qiyas.
c.
Ijtihad
istislah, yaitu menetapkan hukum sesuatu permasalahan dengan menggunakan ra’yu berdasarkan kaidah istishlah/mengambil kemaslahatan.
D.
Syarat-syarat Mujtahid
Seseorang
ulama mujtahid harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1.
Mengetahui seluk-beluk
bahasa Arab dalam semua seginya, yaitu nahu, saraf, bayan, ma’ani dan badi’;
dapat mengetahui lafaz-lafaz yang zahir, sarih, mujmal, haqiqat,
majaz, ’am, khas, muhkam, mutasyabih, mutlaq dan muqayyad.
93Rahmat
Syafe`I, op.cit., hlm. 107
2.
Memiliki pengetahuan
yang cukup
baik
tentang Alquran; mana lafaz yang mantuq,
mafhum, mutlaq, muqayyad, sarih, kinayah, nasikh-mansukh; mengetahui sebab nuzul dan lain-lain.
3.
Memiliki pengetahuan
yang luas tentang sunnah; yakni mengetahui mana hadis yang mutawatir,
ahad, sahih makna haqiqat, majaz, dan lain-lain.
4.
Memiliki pengetahuan yang luas tentang ijma’ dan qiyas.
5.
Menyatakan maksud syara’ dalam
menetapkan hukum.
6.
Memiliki pengetahuan
yang luas tentang usul fikih. Al-Razi
berkata “Ilmu usul fikih adalah
ilmu yang paling penting dimiliki setiap mujtahid.”94
E. Tingkatan Mujtahidin
Menurut sebagaian ulama, ulama-ulama mutjtahidin terbagi
tiga tingkat,
yaitu:
1.
Mujtahid
Mutlaq; melakukan ijtihad berdasarkan kemampuan sendiri, telah memenuhi syarat-syarat mujtahid, seperti empat imam mazhab.
2. Mujtahid Muntasib; telah memenuhi
syarat-syarat mujtahid tetapi menggabungkan diri kepada suatu mazhab; seperti Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dalam mazhab Hanafi; al-Muzanni dalam mazhab Maliki.
3.
Mujtahid Muqayyad; yaitu mujtahid
yang mengikuti salah satu imam mazhab, walaupun berhasil menetapkan hukum sebagai temuannya namun tetap menisbahkannya kepada imam mazhabnya
seperti Hasan ibn Ziyad dari
golongan Hanafi, Ibnu Qayyim dari mazhab Maliki dan
al-Buwaiti dari mazhab Syafi’i.
2. ITTIBA`
a)
Pengertian Ittiba`
94Amir
Syarifuddin, op.cit., hlm. 257-264
Ittiba` secara
bahasa berarti iqtifa` (menelusuri
jejek), qudwah (bersuri teladan) dan uswah
(berpanutan). Ittiba` menurut
istilah menerima perkataan atau ucapan orang lain
dengan mengetahui sumber atau alasan dari perkataan tersebut, baik dalil
Alquran maupun hadis yang dapat dijadikan hujjah /alasan. Sedangkan orang yang mengikuti dengan adanya dalil,
dinamakan muttabi`95.
Firman Allah swt. dalam surah An-Nahl ayat 43 berbunyi :
. التعلملن كنتم إن الذكر اه فسئللآ Artinya: Maka tanyakanlah
olehmu kepada orang yang tahu jika kamu tidak
mengetahuinya.
Dan dalam
surah al-A`raf ayat 2:
كتب انز اليك فال يكن فى صدرك حرج منه لتنذربه وذكرى للمؤمنين . dan Tuhanmu dari kepadamu diturunkan yang keterangan Turutilah : Artinya
janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin
yang lain dari Allah.
Dalam ayat pertama terdapat kalimat “tanyakanlah”
yaitu suatu perintah yang memfaedahkan hal yang wajib untuk dilakukan.
Maksudnya kewajiban kamu bertanya kepada orang yang tahu berdasarkan dari kitab
dan sunnah. Sedangkan pada ayat kedua terdapat pula kalimat “turutilah” yaitu
suatu perintah, yang tiap-tiap perintah wajib untuk dilakukan.96
Sabda Rasulullah Saw.
عليكم
بسنتى وسنة خلفاء الراشدين من بعدي (رواه
ابل داود وغيره ) Rasyidin Khulafaur sunnah dan caraku atau sunnahku turuti Wajib : Artinya
sesudahku. (H.R.Abu Dawud dan lainnya).
b)
Tujuan Ittiba`
Dengan adanya Ittiba`
diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang awam, ia dapat
mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, tanpa diselimuti
keraguan srdikitpun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh
keyakinan akan menimbulkan keikhlasan dan kekhusukan. Keikhlasan dan kekhusukan
merupakan syarat sahnya suatu ibadah atau amal yang dikerjakan.
c)
Jenis-jenis Ittiba`
i.
Ittiba` kepada Allah dan Rasul-Nya
95A.
Hanafi, Ushul Fiqih (Jakarta : Widyaya, tth) hlm. 154
96Ramayulis,
Sejarah dan Pengantar Usul Fiqih, hlm. 208
Ulama sepakat bahwavseluruh kaum muslimin wajib mengikuti segala perintah
Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya. “ikutilah apa yang diturunkan kepadamu
dari Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali
kamu mengambil pelajaran. (QS. al-A`raf 7: 3).
ii.
Ittiba` kepada selain Allah dan Rasul-Nya
Ulama berbeda pendapat tentang ittiba` kepada ulama atau para mujtahid.
Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ittiba` itu hanya dibolehkan kepada
Allah dan Rasul-Nya, dan para sahabatnya saja. Tidak boleh kepada yang lain.
Hal ini dapat di ketahui melalui perkataan beliau kepada Abu Dawud, yaitu :
“Berkata Daud, aku mendengar Ahmad berkata, Ittiba` itu adalah seorang yang
mengikuti apa yang berasal dari Nabi Saw. dan para sahabatnya”.97
3. TAQLID
a)
Pengertian Taqlid
Taqlid adalah
mengikuti atau meniru pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber, alasan dan
tanpa adanya dalil. Menurut istilah menerima suatu ucapan orang lain serta
memperpegangi suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan dan
alasan-alasannya. Orang yang menerima cara tersebut disebut muqalid.98
b)
Syarat-syarat Taqlid
Syarat-syarat taqlid
dapat dibagi dua, yaitu syarat orang yang bertaqlid dan syarat orang yang di taqlidi.
· Syarat ber-taqlid :
Orang yang diperbolehkan untuk bertaqlid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak mengetahui
cara-cara mencari hukum syari`at. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang pandai
dan mengamalkannya.
Adapun orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri
hukum- hukum syari`at maka harus berijtihad
sendiri, bila waktunya masih cukup.
97Drs.
Sudarsono, SH., Pokok-Pokok Hukum Islam,
Pustaka Ceria.
98A.Hanafi,
op.cit., hlm. 157
Tetapi bila waktunya sudah sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan
waktu untuk mengerjakan yang lain (dalam soal-soal ibadah), maka menurut suatu
pendapat boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya.
· Syarat-syarat orang yang ditaqlidi
Syarat orang
yang ditaqlidi terbagi menjadi dua
hukum yaitu :
A.
Hukum akal
Dalam hukum akal tidak boleh ber-taqlid
kepada orang lain seperti mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta
sifat-sifatnya dan hukum akal lainnya. Karena jalan menetapkan hukum-hukum
tersebut ialah akal, sedangkan setiap orang punya akal. Jadi tidak ada gunanya
jika bertaqlid dengan orang lain. Allah Swt. mencela taqlid, sebagaimana
firman-nya :
وإذا قي لهم التبعلا ما انز هللا قالله ب نتبم ماالفينا عليه اباءنا
اوالل
كان
آباؤهم التعقللن شيئا
والتهتدون . Allah, diturunkan yang perintah ikutilah mereka, kepada dikatakan Apabila Artinya: peroleh kami yang apa-apa mengikuti kami tetapi : menjawab mereka maka
dari orang tua kami. Meskipun orang tua mereka tiada memikirkan sesuatu
apa pun dan tidak pula mendapat petunjuk. (al-Baqarah :170)
B. Hukum syara`
Hukum syara`
dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
a.
Yang diketahui dengan pasti dari agama seperti wajib
salat lima waktu, puasa, zakat dan haji, juga
tentang haramnya zina dan minuman keras. Dalam soal-soal tersebut tidak boleh taqlid, karena semua orang dapat mengetahuinya.
b.
Yang diketahui dengan penyelidikan dan mencari dalil,
seperti soal-soal ibadah yang kecil, dalam hal semacam ini diperbolehkan taqlid.
Tidak hanya taqlid
yang diperbolehkan saja yang ada, tetapi taqlid yang diharamkan juga ada, yaitu :
1)
Taqlid semata-mata
mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang
bertentangan dengan Alquran dan Hadis.
2)
Taqlid kepada
orang yang tidak diketahui bahwa dia
pantas diambil perkataannya.
3) Taqlid kepada perkataan atau pendapat
seseorang, sedangkan yang bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat
itu salah.99
BAB IV
KAEDAH-KAEDAH USULIYYAH
A.
Pengertian Kaedah Usuliyyah
99Ibid.,
hlm. 158.
Istinbat
al-Ahkam dari nas Alquran
dan Hadis bisa ditempuh melalui dua
cara, yaitu pendekatan kaidah-kaidah lughawiyah
(usuliyyah); dan pendekatan kaidah-kaidah tasyri’iyyah. Sebelum dijelaskan lebih lanjut terlebih dahulu dikemukakan pengertian
dari kaidah usuliyyah tersebut.
Kaedah berarti aturan umum. Usuliyyah berarti pokok dan meyeluruh, yakni bukan hanya suatu
hukum tertentu. Dengan demikian kaedah usuliyyah
adalah aturan umum yang digunakan untuk menggali hukum. Kaedah usuliyyah berkaitan dengan lafaz dan dalalahnya atau lebih tepatnya berkaitan
dengan kebahasaan (Arab)100 Pembahasan yang berkaitan dengan
kebahasaan cukup banyak antara lain wadih
dan mubham, ‘am dan khas, amr dan nahi, mutlaq dan muqayyad dan lain-lain.
B.
‘Am dan Khas
‘Am menurut ulama
Hanafiyyah adalah setiap lafaz yang mencakup banyak baik dari segi lafaz maupun makna. Menurut Syafi’iyyah
suatu lafaz yang dari satu segi menunjukkan dua makna atau lebih.101 Sementara Uddah
(dari Hanbali)
membuat rumusan suatu lafaz yang mencakup dua hal atau lebih.102
Lafaz-lafaz
yang menunjukkan ‘am ada sepuluh
macam.103 yaitu:
1.
Suatu Lafaz yang diidafahkan
kepada ma’rifah.
صالة الجمعة , نعمة هللا Contoh:
2.
Alif lam masuk kepada isim jama’.
Seperti: الرجال
3.
Isim mufrad yang memakai
alif lam, disebut alif lam
jinsiyyah.
االنسان Seperti:
4.
Isim syarat, yaitu man,
ma, ayyu dan aina.
فمن شهد Contoh:
ما تنفقوا,
أي كتاب,
أين
ما تكون,

100Kamal
Mukhtar dkk., op. cit., hlm.186.
Lihat juga: Rahmat Syafe`I, op.cit.,
hlm. 147.
101Ibid., hlm. 193.
102Amir
Syarifuddin, op.cit., hlm. 46-47.
103Kamal
Mukhtar, dkk., jilid II, op. cit.,
hlm. 8-16
6.
Isim nakirah dimasuki
nafi, nahi atau syarat.
ال تبطلوا صدقاتكم ,ال وصية لوارث , ان جاءكم فاسق Contoh:
7.
Isim nakirah yang diberi sifat dengan sifat umum.
رجل
صالح , عبد مؤمن Seperti:
8.
Lafaz-lafaz yang menunjukkan berlaku umum.
سائر , معشر , عامة , كافة Seperti:
9. Kata yang diidafahkan kepada كل dan جميع
جميع الناجحين , كل عمل Seperti:
10.
Lafaz `amr ditujukan kepada jama’.
أقيموا الصالة Seperti:
Menurut Al-Khudari
Bek, khas adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu arti secara mandiri. Al-Amidi merumuskan khas adalah suatu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak.104 Lafaz khas
itu menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu seperti Musa, atau menunjukkan suatu macam/jenis seperti rajulun
(seorang laki-laki), imra`atun
(seorang wanita) atau bilangan tertentu seperti tiga, seratus, seribu. Lafaz khas itu dapat ditujukan kepada
benda yang
konkrit seperti contoh-contoh di atas, atau yang abstrak seperti ilmu, kecerdasan,
kebodohan dan lain-lain.105
Menurut jumhur ulama usul,
lafaz ‘am pada umumnya ditujukan
kepada sebagian satuan-satuannya saja, sehingga dikalangan ulama terkenal kaidah ماا
خا اال
عاام
مان (tidak
ada sesuatu
yang umum
melainkan dibatasi).
Lebih jelasnya
bahwa menurut jumhur ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah, dilalah ‘am adalah zanniy. Ibnu Abbas berkata:
ليس فى القران عام االخصص اال قلله تعالى : وهللا بك شيء عليم
Artinya: Semua lafaz umum dalam Alquran ada takhsisnya, kecuali firman-Nya:
“Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
104Amir
Syarifyddin, op.cit., hlm. 83.
105Kamal
Mukhtar, dkk., jilid II, op.cit.,
hlm. 6.
Menurut Hanafiyah
dilalah ‘am itu qat’iy, kecuali
ada dalil yang mengubahnya. Dengan demikian,
menurut jumhur ulama, hadis ahad
dapat mentakhsis lafaz Alquran
yang dilalahnya zanniy, sedang
menurut Hanafiyah, hadis ahad
tidak dapat mentakhsis ayat Alquran.
Karena itulah ulama Hanafiyah
berpendapat tidak wajib “
tertib “
dalam wudu` sebab ayat wudu` (surah al-Ma`idah ayat 6) jelas tidak memerintahkan tertib berwudu`, walaupun ada hadis yang menyatakan
wajib tertib berwudu`,
hadis tersebut tidak dapat mengkhususkan (mentakhsis) keumuman ayat wudu`.
Sedang menurut jumhur wajib
tertib dalam berwudu` dengan hadis. Maknanya: Allah tidak menerima shalat seseorang sehingga ia bersuci
sesuai tertib pelaksanaanya, maka hendaklah
ia membasuh wajahnya kemudian dua tanggannya (hadis ini mengkhususkan ayat wudu`). Lain pula pendirian
Imam Malik tentang
tertib dalam wudu`. Walaupun beliau sependapat
dengan jumhur, bahwa hadis
ahad dapat mentakhsis lafaz ‘am Alquran,
hadis ahad tersebut harus
didukung oleh pengamalan Ahlu Madinah. Berhubung hadis di atas tidak didukung pengamalan
Ahlu Madinah, maka Imam Malikpun tidak mewajibkan tertib
dalam wudu`.106
C.
Amr dan Nahi
Amr adalah suatu tuntutan dari atasan kepada
bawahan untuk mengerjakan suatu
pekerjaan.107 Sigat (bentuk
kata) yang menunjukkan Amr ada enam macam
yaitu :
1.
Fi’il amr
2. Fi’il mudari’ yang dimasuki lam amr, seperti: ولتكن
3.
Isim fi’il amr seperti: أنفسكم
عليكم (jagalah dirimu)
4. Masdar pengganti fi’il amr, seperti: احسانا
وبالوالدين
5.
Jumlah khabariyyah yang mengandung
arti insya`iyyah
seperti:
106Rahmat
Syafe`I, op.cit., hlm. 194-198.
107Muhammad Adib Salih, Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami,
jilid I, ( Beirut : al-Maktab al- Islami, 1984), hlm. 234
والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثالثة قرؤ
Artinya: Wanita-wanita
yang ditalak suaminya, hendaklah menunggu ‘iddah
mereka tiga quru’.
6.
Kata-kata yang mengandung makna perintah, seperti “amara, farada, kutiba”.108
Makna lafaz amr menurut aslinya
adalah menunjukkan wajib. Tetapi digunakan juga kepada makna lain (bukan wajib). Makna yang bukan wajib tersebut
dapat dipahami dari pekerjaan yang akan dilakukan
atau perbuatan yang disuruh
dengan amr yang bersangkutan. Makna-makna amr tersebut antara lain : 109
1.
Nadab (sunat dikerjakan),
seperti membuat perjanjian dengan
budak yang ingin dimerdekakan, kelihatannya mampu menebus dirinya dengan sejumlah pembayaran. Firman Allah pada surah an-Nur ayat 33:
فكاتبلهم ان علمتم فيهم خيرا
Artinya: Maka hendaklah
kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka.
2. Irsyad (memberi tuntunan),
seperti suruhan mengambil saksi dalam jual-beli
tertentu. Firman Allah pada
surah al-Baqarah ayat 282:
وأشهدوا اذا تبايعتم
Artinya: Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.
3. Ta’dib (bersopan santun); seperti: “makanlah
apa yang ada di dekatmu”.
4.
Ibahah (boleh dilakukan atau tidak dilakukan), seperti: “makan dan minumlah kamu: (surah al-Baqarah ayat 60).
5. Tahdid (mengancam), seperti: “lakukanlah apa yang kamu kehendaki” (surah
Fhussilat ayat 40).
6. Ikram (memuliakan), seperti: “Masuklah kamu ke
dalamnya (surga) dengan selamat dan tentram” (surah al-Hijr ayat 46).
108Kamal
Mukhtar, dkk., jilid II, op.cit., hlm. 27-29.
109Ibid., hlm. 30-34.
7. Taskhir (menghina), seperti: “Jadilah
kamu kera yang hina”
(surah al-Baqarah
ayat 65).
8.
Ta’jiz (menunjukkan kelemahan mukhatab), seperti: “Buatlah satu surat saja yang setara
dengan Alquran” (surah al-Baqarah ayat 23).
9. Do’a, seperti: “Turunkanlah rahmat kepada kami”.
Nahi adalah tuntutan untuk
meninggalkan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Sigat yang menunjukkan nahi ada tiga macam : 110
1. Fi’il mudari’ yang didahului la nahi, seperti: الزنا
تقربوا ال
2.
Perintah meninggalkan suatu pekerjaan, seperti: الزور قول اجتنبوا
3.
Lafaz-lafaz yang menunjukkan haram, seperti: الربا حرم , رفث فال
Adapun makna nahi
pada dasarnya menunjukkan haram. Namun digunakan juga kepada makna lain,
yaitu : 111
1.
Makruh, seperti hadis yang menyatakan: “janganlah minum dengan tangan kirimu”.
2.
Irsyad (memberi bimbingan), seperti: “janganlah kamu menanyakan hal-hal
yang jika diterangkan akan menyusahkan kamu” (surah al-Ma`idah ayat 10).
3.
Al-Dawam/berkekalan,
langgeng, seperti: “sekali-kali janganlah kamu menyangka
bahwa Allah lalai dari pada yang diperbuat
orang-orang zalim” (surah Ibrahim ayat 42).
4.
Menerangkan akibat, seperti: “janganlah kamu mengira bahwa
mereka yang gugur di jalan itu mati,
tetapi mereka itu hidup” (surah
Ali Imran ayat 169).
5.
Menyatakan keputusan, seperti: “Hai orang-orang kafir
janganlah kamu membuat
alasan (untuk dapat diampuni) pada hari ini” (surah Ibrahim ayat 7).
110Ibid., hlm. 27-29.
111Ibid., hlm. 49-52
6.
Menghibur, seperti: “Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita”
(surah at-Taubah ayat 40).
7.
Tamanni (berangan-angan) seperti: “Hai malam panjanglah!”
8.
Mencaci, seperti: “Janganlah engkau
melarang orang berperilaku dengan perbuatan yang jelek sedang
engkau sendiri melakukan yang sama
dengannya”.
9.
Tahdid (menghardik,
mengancam), seperti:
“Jangan dengarkan nasehatku!”
10.
Do’a, seperti: “Ya Allah, janganlah
azab kami pada hari kiamat”.
11.
Iltimas (ucapan kepada teman),
seperti: “Janganlah banyak merokok!”.
D.
Mutlaq dan Muqayyad
Mutlaq adalah lafaz
yang belum ada batasannya atau
belum ada ikatannya dengan kata lain, seperti
guru, siswa, buku, burung, kayu dan sebagainya. Bila
dibatasi dengan lafaz lain, umpamanya:
guru madrasah, siswa Aliyyah,
buku pelajaran fisika, burung beo, kayu jati, maka jangkauan pengertian masing-masing lafaz tersebut telah dibatasi atau semakin sempit bila dibandingkan dengan sebelum dihubungkan dengan lafaz
lain. Masing-masing lafaz tersebut setelah dikaitkan/dihubungkan dengan
lafaz lain, disebut muqayyad.
Para ulama usul
fikih merumuskan defenisi mutlaq dan muqayyad yang redaksinya
berbeda-beda namun pengertiannya
sama
dengan pengertian di atas, antara lain: “Mutlaq adalah lafaz
yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa.”112
“Muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan
hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit
keluasan artinya.”113
Berbicara tentang hukum mutlaq dan muqayyad, ada
empat macam hukum yang telah disepakati ulama, yaitu:
1. Lafaz mutlaq sesuai
dengan mutlaqnya, karena tidak ada dalil yang
menunjukkan kepada muqayyad. Contoh, haram menikahi ibu
si istri (surah an-Nisa’ ayat 23).
112Amir
Syarifuddin, op.cit., hlm. 116
113Rahmat
Syafe`I, op.cit., hlm. 212
Dalam ayat ini mutlaq ibu istri
baik seseorang itu telah mencampuri istrinya atau belum.
2.
Lafaz mutlaq yang ada taqyidnya, maka diamalkan
secara muqayyad. Contoh: lafaz wasiyyat pada surah an-Nisa` ayat 11 adalah mutlaq tanpa batas apakah separuh,
sepertiga atau seluruh harta peninggalan. Tetapi
pada hadis ditemukan bahwa wasiat itu maksimal sepertiga. Dengan demikian
lafaz wasiyyat pada ayat tersebut menjadi muqayyad dengan hadis.
3.
Lafaz muqayyad diamalkan tidak muqayyad karena ada dalil yang
menghapuskan muqayyadnya. Contoh: pada surah an-Nisa’ ayat 23 dinyatakan haram
mengawini anak tiri dengan dua batasan. Batasan
pertama berada dalam pemeliharaan ayah tiri. Batasan kedua bahwa
ibu kandung anak tiri itu
sudah dicampuri. Menurut batasan
pertama yakni anak tiri yang dalam pemeliharaan
ayah tiri yang haram dikawini. Bila anak
tiri itu tidak dalam pemeliharaan
ayah tiri berarti boleh dikawini ayah tiri. Namun dalam hal ini, lafaz
yang menyatakan “dalam pemeliharaan
ayah tiri” sebagai lafaz muqayyad tidak
diamalkan, sehingga semua anak tiri baik dipelihara di rumah ayah tiri maupun berada di tempat lain tetap haram dikawini bila ibunya
sudah dicampuri. Dalil yang menujukkan
bahwa batasan yang pertama
tidak diamalkan dengan dua alasan:
a.
Pada ayat itu
dinyatakan bahwa boleh mengawini anak tiri bila ibunya tidak dicampuri, tidak disebutkan bila anak tiri itu berada dirumah
lain.
b.
Bila anak tiri yang berada di rumah lain boleh
dikawini, tentu seseorang akan
mengawini seorang perempuan bersama-sama
dengan anak perempuan tersebut. Ini tidak mungkin dibenarkan dalam Islam.
4. Lafaz Muqayyad, diamalkan tetap sebagai muqayyad, karena tidak ada dalil yang menghapuskan
batasan/taqyidnya. Contoh: kifarat zihar adalah memerdekakan seorang budak, kalau tidak ada atau tidak mampu maka puasa dua bulan berturut
turut sebelum mencampuri istrinya (surah al-Mujadilah ayat 3-4).
Puasa dua bulan berturut-turut sebelum bercampur
adalah lafaz muqayyad. Bagi yang menzihar istrinya wajib mengamalkan kifarat
tersebut. 114(Mukhtar, dkk., 1995b:56-59).
114Kamal
Mukhtar
BAB V
KAEDAH-KAEDAH FIQHIYYAH
A. Definisi Kaedah Fiqhiyyah
Telah diungkapkan
pada bagian awal bab sebelumnya bahwa dalam memahami nas, ditempuh dua cara agar pesan-pesan imperatif yang terkandung
pada setiap nas tersebut dapat
ditangkap dengan baik dan pada gilirannya terealisasikan dengan baik pula. Setelah mengemukakan seperlunya kaedah usuliyyah yang titik tekannya ada pada aspek kebahasaan, maka pada bab ini dijelaskan kaedah fiqhiyyah yang menekankan pada jiwa atau semangat ajarannya.
Seperti telah termaklumi
bahwa kaedah berarti aturan umum yang menjadi pedoman bagi kasus-kasus yang
bersifat spesifik (furu’). Jika kata kaedah tersebut dirangkaikan
dengan fiqhiyyah (susunannya
berbentuk na’at dan man’ut, dengan penambahan ya nisbah pada
kata fiqh) berarti aturan umum bertalian dengan masalah-masalah fikih, atau patokan-patokan hukum fikih yang bersifat umum yang
diambil dari dalil-dalil yang bersifat
umum (Alquran dan Sunnah)
Terdapat beberapa definisi
yang dirumuskan oleh para ulama usul
(usuliyyin) mengenai kaedah fiqhiyyah,
satu di antaranya adalah pendapat Ali Hasaballah,115
yang menyatakan “sekumpulan aturan (pedoman) yang dibuat oleh syari’ dalam menetapkan
hukum (tasyri’) dan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam membuat pembebanan hukum (taklif)”.
Mengingat kaedah-kaedah
fiqhiyyah ini bersifat kulli (umum)
maka disebut juga kaedah kulliyah. Perlu dimaklumi bahwa masing-masing kaedah fiqhiyyah dirumuskan berdasarkan
cukup banyaknya masalah furu’ yang masuk
dalam cakupannya, dalam arti tidak tertutup kemungkinan terdapat satu atau beberapa masalah furu’ yang tidak tepat digolongkan dalam kaedah-kaedah fiqhiyyah tersebut..
115Ali Hasaballah, Usul at-Tasyri` al-Islami, (Kairo : Dar al-Ma`arif, t.t.), hlm. 293
Untuk lebih
jelasnya pengertian kaedah fiqhiyyah tersebut
diambil salah satu contoh kaedah yang berbunyi:
االجتهاد الينقض باالجتهاد
Maksudnya: Hasil ijtihad yang sudah lalu tidak dibatalkan
dengan Ijtihad yang
datang kemudian.116 (Rahman, 1986:10).
B. Urgensi
Kaedah Fiqhiyyah
Area pembahasan fikih Islam
itu sangat luas, mengingat fikih
Islam menetapkan hukum yang mencakup
hubungan hamba dan Khaliqnya, antar hamba dengan hamba baik urusan pribadi, maupun menyangkut masyarakat,
bangsa dan negara serta hubungan internasional bahkan menyangkut dengan jenazah,
juga mengatur perlakuan terhadap hewan-hewan, dan alam lingkungan.
Memperhatikan luasnya
cakupan pembahasan fikih Islam,
cukup berat bagi para mujtahid untuk
menetapkan hukum setiap masalah furu’ yang
tidak terhitung jumlahnya dan
terus berkembang. Para ulama usul fikih membuat kaidah-kaidah fiqhiyyah, di mana setiap kaidah
memiliki cakupan yang cukup
banyak masalah furu’nya sehingga masalah-masalah furu’ tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kumpulan tersendiri, setiap kumpulan
bernaung di bawah satu kaidah.
Dengan demikian para
mujtahid merasa lebih mudah untuk menetapkan hukum suatu masalah yakni dengan
menempatkannya pada salah satu kaidah fiqhiyyah
yang lebih tepat untuk masing-masing masalah furu’. Dapat dipahami bahwa kaidah
fiqhiyyah adalah perluasan secara umum dari
hukum-hukum furu’ yang banyak jumlahnya dan seragam. Mengetahui
kaidah-kaidah fiqhiyyah, berperan memudahkan memberi fatwa.
Dapat disimpulkan bahwa urgensi kaidah-kaidah fiqhiyyah adalah sebagai berikut:
1.
Sebagai salah satu jalan mendalami fikih
2.
Mengantarkan seseorang fakih mampu menganalisis berbagai masalah
fikih.
3.
Memudahkan untuk memahami hukum
suatu kasus.
116
Asjmuni A Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqih,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 16-19
C. Perbedaan
Kaidah Fiqhiyyah dengan Kaidah Ushuliyyah
1.
Objek kaedah fiqhiyyah
adalah perbuatan
mukallaf, sedang objek kaidah usuliyyah
adalah dalil
hukum.
2. Ketentuan
kaedah fiqhiyyah berlaku pada sebagian besar hukum-hukum furu’
(bukan semuanya), sedang kaidah usuliyyah
berlaku pada semua hukum-hukum furu’.
3. Kaedah fiqhiyyah bersifat ukuran/keadaan
suatu masalah, sedang kaidah usuliyyah
bersifat kebahasaan.
4. Kaedah fiqhiyyah pada dasarnya untuk memudahkan memahami hukum fiqih, sedang kaidah usuliyyah sebagai sarana untuk mengistinbatkan hukum.117
D. Kaedah Asasiyyah
Kaedah asasiyyah
berarti aturan umum/undang-undang yang pokok, maksudnya kaedah asasiyyah tersebut
menjadi rujukan/tempat berpijak atau dasar semua kaedah fiqhiyyah.
Sebagian ulama menetapkan bahwa seluruh kaedah fiqhiyyah
(jumlahnya ada yang mengatakan 40 buah, 86 buah, 160 buah dan lain- lain)
merujuk kepada lima buah kaedah yang disebut “Panca Kaedah
Kulliyah/Fiqhiyyah”.
Syekh ‘Izzuddin
Ibnu Abdis Salam mengembalikan semua kaedah fiqhiyyah kepada
satu kaedah saja yaitu “Dar al-mafasid wa jalbu al-mashalih” (menolak
kerusakan dan menarik kemaslahatan). Ini sesuai dengan hakikat ketentuan hukum yang keseluruhannya dimaksudkan demi memenuhi kebutuhan manusia.118
Panca kaedah fiqhiyyah tersebut adalah:
1.
Al-umuru bi maqasidiha. ( بمقاصدها األمر
(
2.
Al masyaqqah tajlibu al-taisir .( التيسير
تجلب المشقة
)
117Rahmat
Syafe`I, op.cit., hlm. 254-255
118Muhammad
Sa`id Ramadan al-Buti, Dawabit
al-Maslahah fi asy-Syari`ah al-Islamiyyah,
(Damaskus: Ad-Dar al-Muttahidah, 1992) hlm. 69.
3.
Al-Dararu
yuzal.
(
يزال
الضرر )
4.
Al-Yaqinu la yuzalu bi al-syak.
( بالشك يزال ال اليقين ) 5. Al ‘adatu muhakkamah. (محكمة العادة ).119
E.
Kaedah-kaedah yang Berkaitan dengan Kaedah Asasiyyah
Bagian ini memuat pembahasan beberapa kaedah yang
masuk dalam cakupan masing-masing kaedah asasiyyah
yang terdiri dari lima kaedah. Telah disebutkan bahwa kaedah-kaedah fiqhiyyah merujuk kepada lima buah
kaedah pokok tersebut.
1. Kaedah pertama, Al umuru bi maqasidiha ( بمقاصدها األمر
) Artinya semua pekerjaan
itu menurut maksud pelakunya. Kaedah-kaedah
yang termasuk dalam cakupan ini antara lain:
-3 ماال يشترط التعرض له جملة او تفصيال اذا عينه و
أخطأ لم يضر
Artinya: Suatu amal
yang tidak disyaratkan penjelasannya baik secara global atau terinci walaupun ditentukannya dan ternyata salah, tidak merusak amal tersebut.
Contoh: Dalam shalat tidak disyaratkan niat menyebutkan
jumlah rakaat, walaupun meniatkan shalat maghrib 4 rakaat tapi dilaksanakan
3 rakaat, shalatnya tetap syah.
-2 النية فى اليمين تخصص اللفظ العام والتعم الخاص
Artinya: Niat
dalam sumpah mengkhususkan lafaz
yang umum, bukan mengumumkan lafaz yang
khusus.
Contoh: Jamal
bersumpah tidak akan berbicara dengan
seseorang, maksudnya dengan Latief, maka sumpahnya hanya berlaku kepada
si Latief saja, tidak kepada semua orang.120
2. Kaedah kedua: التيسااير
تجلااب المشااقة. Artinya:
kesukaran
itu mendatangkan
kemudahan. Kaedah-kaedah yang bernaung di bawah kaedah ini, antara lain:
-3 األمر اذا
ضاق اتسم
Artinya: Suatu masalah apabila sempit menjadi luas
119
Rahmat Syafe`I, op.cit., hlm. 270-274
120Rahmat
Syafe`I, op.cit., hlm. 277-279.
Contoh: Seseorang yang sakit boleh berbuka puasa, boleh shalat fardhu
dengan berbaring.
-2 الرخص ال تناط بالمعاصى
Artinya:
Keringanan-keringanan itu tidak boleh
dikaitkan dengan kemaksiatan. Contoh: Musafir untuk melakukan maksiat
tidak boleh berbuka puasa.
3. Kaedah Ketiga: يازال الضارر Artinya: Kemudratan itu harus dihilangkan. Kaedah- kaedah dalam cakupannya antara lain:
-3 الضرورات تبيح المحظلرات
Artinya: Kemudaratan itu membolehkan melakukan yang dilarang.
Contoh: Seseorang yang kelaparan boleh makan daging babi bila hanya
daging babi yang ada.
-2 ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها
Artinya: Apa yang dibolehkan karena kemudaratan di
ukur menurut kadar kemudlratannya.
Contoh: Kebolehan makan daging babi, jangan sampai
kenyang, cukup sekedarnya saja.
4. Kaedah keempat: بالشاك يازال
ال اليقاين Artinya: Keyakinan
tidak dapat dihilangkan
dengan adanya keraguan.
Kaedah-kaedah yang tergolong dalam kelompok kaedah ini antara lain:
-3 األص بقاء ما كان على ما كان
Artinya:
Hukum asal, tetap keadaannya menurut keadaan yang telah lalu.
Contoh: Seorang debitur mengatakan telah melunasi utangnya kepada kreditur, sedang
kreditur bersumpah belum menerimanya
maka dihukumkan debitur belum melunasi
utangnya, kecuali ada bukti lain.
-2 ان ما ثبت بيقين ال يرتفم اال بيقين
Artinya: Sesuatu yang sudah
ditetapkan dengan yakin tak dapat dihilangkan kecuali dengan yakin pula.
Contoh: Seseorang yang telah berwudu’
ia tetap suci dari hadas kecuali ia yakin
wudu`nya telah batal.
5. Kaedah kelima: محكماة العاادة Artinya:
Adat kebiasaan dapat
ditetapkan
sebagai
hukum. Perlu diperjelas bahwa adat yang ditetapkan sebagai
hukum adalah kebiasaan yang berlaku
dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas serta
jiwa syariat Islam. Kaedah-kaedah yang termasuk dalam wilayah kaedah ini, antara lain:
-3 استعما الناس حجة تجب العم بها
Artinya: Apa yang biasa dilakukan
orang banyak, merupakan dalil yang wajib diamalkan.
Contoh: Benda-benda berat yang diperjualbelikan, biaya mengangkutnya ke
rumah pembeli ditanggung oleh penjual.
-2 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
Artinya: Menentukan sesuatu berdasarkan ‘urf seperti menentukan berdasarkan nas.
Contoh: Makan di rumah makan terlebih dahulu dimakan baru ditanya harganya/dibayar.121
121Kamal
Mukhtar, dkk. Jilid II, op.cit., hlm.
198-216.
BAB VI MAQASID AS-SHAR`IYYAH
A.
Pengertian Maqasid as-Shar`iyyah
Secara
lughawi, Maqasid as-Shari`iyyah terdiri
dari dua kata, yakni maqasid dan as-shar`iyyah. hubungan Maqasid dengan as-Shari`iyyah dalam bentuk mudhaf
dan mudhafun ilaih. Maqasid adalah bentuk jama` dari maqsud yang berarti kesengajaan,
maksud atau tujuan. Syariat secara bahasa berarti الماء الى
yang berarti jalan menuju sumber air.
Jalan menuju sumber air
ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.
Kata syariah yang sejatinya berarti
hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi
sebagai penjelas atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid
berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.
Dihubungkannya kata syariat kepada kata maksud, maka kata syariat berarti pembuat hukum atau syari`. Dengan demikian kata Maqasid
as-Shar`iyyah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum,
apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh
Allah dalam menetapkan suatu hukum.122
Adapun tujuan syariat (maqasid
as-syar`iyyah) adalah untuk kemaslahatan manusia. As-Syatibi menulis :
هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصالحهم فى الدين والدنيا معا di manusia kemaslahatan mewujudkan bertujuan itu syariat Sesungguhnya : Artinya
dunia dan di akhirat.123
122
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jakarta : CV. Mulya, 1996, hlm. 78
123Jumantoro,
Totok & Munir, samsul, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta : Amzah, 2008, hlm.
196
B. Pembagian Maqasid as-Syar`iyyah.
Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa
maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :
1.
Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan
primer manusia (Maqashid al-Dharuriyyat)
Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah kami
uraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu : Agama, jiwa, akal,
kehormatan (nasab), dan harta. Islam
telah mensyariatkan bagi masing- masing lima perkara itu, hukum yang menjamin
realisasinya dan pemeliharaannya, lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah
bagi manusia kebutuhan primernya.
a)
Agama
Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan
undang- undang yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan
manusia dengan Tuhan-nya (hubungan vertikal)
dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah yang tertinggi
dan sempurna seperti dinyatakan dalam Alquran surat al- Maidah ayat 3. Yang
berbunyi :
Artinya :
Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi
agama bagimu.
Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan
utama yang harus dipenuhi karena agama lah yang dapat menyentuh nurani manusia,
seperti perintah Allah agar kita tetap berusaha menegakkan agama, seperti
firman Allah dalam surat asy-syura ayat 13.
Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang
yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah dan akhlaknya
atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran islam dengan berbagai paham
dan aliran yang batil. Walaupun begitu, agama Islam memberi perlindungan dan
kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan
melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakininya, orang-orang islam
tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini seperti yang telah
ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 256.
b)
Memelihara Jiwa
Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan)
sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan
pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh
mati, maka seseorang yang membunuh
tersebut juga akan mati.
Berikut adalah salah satu contoh ayat yang melarang
pembunuhan terjadi di dunia, yaitu surat al-Isra`
ayat 33
Artinya :
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar. Dan
barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.
c)
Memelihara Akal
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara
seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia
dengan sebaik-baik bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal.
Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah
melarang minum khamar (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal.dan menghukum
orang yang meminumnya. Begitu banyak
ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Kita disuruh
untuk memetik pelajaran kepada
seluruh hal yang ada di bumi ini, termasuk
kepada binatang ternak, kurma hingga lebah, seperti yang tertuang dalam
surat an-
Nahl ayat
66-69.
d)
Memelihara Keturunan
Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina,
menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara
perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi,
sehingga perkawinan itu dianggap sah dan
percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap
zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi
keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tapi juga
melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang
dapat membawa pada zina.
e)
Memelihara Harta Benda
Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu
kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena
manusia sangat tama` kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan
apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan
peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan
lain-lain.124
2.
Syariat yang berhubungan
dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia (Maqashid al-Hajiyat)
Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia
bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia,
meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah ( tukar menukar). Islam telah mensyariatkan sejumlah
hukum dalam berbagai ibadah, muamalah dan
uqubah (pidana), yang dengan itu
dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.
Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan, kelapangan) untuk
meringankan beban mukallaf apabila
ada kesulitan dalam melaksanakan hukum Azimah
(kewajiban). Contoh, diperbolehkannya berbuka puasa pada siang hari bulan
Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian.
Dalam lapangan muamalah,
Islam mensyariatkan banyak macam akad (kontrak) dan urusan (tasharruf) yang menjadi kebutuhan
manusia. Seperti
124Ismail
Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam,
Jakarta : Bumi Aksara, 1992, hlm. 67-101
jual
beli, syirkah (perseroan), mudharabah (berniaga dengan harta orang lain)
dan lain-lain.
3.
Syariat yang berhubungan
dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (Maqashid al-Tahsini).
Manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang
bersifat pelengkap, ketika Islam mensyariatkan bersuci (thaharah), disana dianjurkan beberapa hal yang dapat
menyempurnakannya seperti tertib. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (tatahawwu`), maka Islam menjadikan
ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya, sehingga seorang
mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum
sempurna.
Ketika Islam menganjurkan derma (infaq), dianjurkan agar infaq dari
hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah, bahwa tujuan dari setiap hukum
yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia, atau kepentingan
sekundernya atau kepentingan pelengkapnya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara tiga
kepentingan tersebut.125
C.
Kedudukan Maqashid as-Syar`iyyah
Dalil-dalil syariat Islam menegaskan bahwa setiap
hukum-hukumnya mempunyai maqashid atau
maksud yang tertentu Tujuan pensyariatan itu untuk kemaslahatan manusia di
dunia dan akhirat. Maqasid as-Syar`iyyah merupakan tolak
ukur dalam menilai sesuatu. Dengan kata lain,
dalam memahami sesuatu hukum harus seiring dengan maqashid yang telah digariskan oleh syara`. Fenomena ini jelas terlihat di dalam Alquran dan al-Sunnah.
Jumhur ulama telah berpendapat bahwa hukum-hukum syara` mengandung hikmah dan maqashid
tersendiri, yang berkisar tentang menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan
di akhirat. Pengamatan terhadap hukum-hukum ini telah menghasilkan satu jalinan
yang kuat antara hukum syara` dan maqashidnya.
125Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 333-343.
Dalam proses memahami hukum, seorang faqih perlu
memahami dalil-dalil hukum dan memandang lebih jauh lagi aspek maqasid hukum tersebut disyariatkan.
Malah dapat dikatakan hukum fiqih tanpa maqasid
sama seperti jasad yang tiada ruhnya.
Dalil-dalil yang mengukuhkan kedudukan maqashid sebagai hujjah yang mengikat :
· Alquran
Alquran merupakan sumber primer maqashid as-Syar`iyyah sama ada secara langsung atau pun tidak,
dari Alquran dapat diketahui maqashid pengutusan
rasul-rasul, penurunan Alquran, pentaklifan
mukallaf dengan tanggungjawab dan pembalasannya dan maqashid kejadian alam dan manusia.
· Al-Sunnah
Sebagai sumber kedua setelah Alquran, al-Sunnah
mempunyai peranan penting dalam menguatkan apa yang dibawa oleh Alquran.
Menafsirkan Alquran, menjelaskan dan menguraikannya
agar lebih jelas dan mudah
dipraktekkan. Banyak sekali al-Sunnah menerangkan sesuatu hukum turut
menekankan aspek maqshid hukum
tersebut. Contoh hadis Rasulullah Saw. yang
artinya : “Sesungguhnya agama itu mudah”. Hadis ini menunjukkan maqashid memudahkan ummat tidak
membebankan dan senang untuk diamalkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah
bersabda : “Jika tidak memberatkan ummatku niscaya aku suruh mereka bersiwak
untuk setiap kali shalat” dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa syariat Islam
bertujuan memudahkan ummat dan memastikan kemaslahatan mereka terjamin.
· Ijtihad
Pada masa sahabat
mereka telah mengaplikasikan konsep maqashid
as- syar`iyyah dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan. Jika dibandingkan
dengan masa Rasul Saw. penggunaan konsep maqashid
as-syar`iyyah pada masa sahabat lebih banyak digunakan karena banyaknya
perkara-perkara baru yang tidak ada nas nya.
Pemahaman para sahabat terhadap Alquran sangat
istimewa dibandingkan dengan pemahaman orang lain, karena mereka bukan saja
memahami zahir ayat Alquran tetapi
menjangkau tujuan dibalik turunnya Alquran. Kita dapati ijtihad-ijtihad mereka
sesuai dengan kehendak syara` untuk menjamin kemaslahatan ummat. Contoh ijtihad
sahabat mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf,
menjatuhkan talak tiga dengan satu lafaz,
tidak membagikan tanah rampasan perang kepada tentara, dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Slamet, dan Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat 1, Bandung : CV.
Pustaka Setia
ad-Dabusi,
Abu Zaid ‘Abd Allah ibn ‘Umar. t.t. Taqwim
al-Adillah. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
al-Amidi, Abu al-Hasan ‘Ali ibn
Muhammad. 1404 H. Al-Ihkam fi Usul al-
Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi. Jilid II.
Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, t.t., Fath al-Wahhab, Singapura : Sulaiman
Mar`iy.
Al-Asfahani, al-Raghib, Mu`jam Mufradat Alfaz Alquran, Beirut :
Dar al-Fikr, t.t.
al-Bazdawi,
Fakhr al-Islam ‘Ali ibn Muhammad ibn al-Husain. 1308 H. Kasyf al-Asrar ‘ala Usul al-Fiqh. ttp.: Maktab as-Sanayi’. Jilid I.
al-Bukhari,
Abd al-‘Aziz. 1307 H. Kasyf al-Asrar
Syarh Usul al-Bazdawi. ttp.: Maktab as-Sanayi’. Jilid I.
al-Buti,
Muhammad Sa’id Ramadan. 1992. Dawabit
al-Maslahah fi asy- Syari’ah al-Islamiyyah. Damaskus: Ad-Dar al-Muttahidah.
Cet. VI.
Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqri, 1994, al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al
Kabir li al-Rafi`I, Beirut : Dar al-Kutub al- Islamiyah.
Al-`Ikk,
Khalid Abdurrahman, 2009, Fikih Wanita,
Semarang : Pustaka Rizki Putra.
Al-Jassas.
t.t. Usul al-Fiqh. Kairo: Dar
al-Kutub al-Misriyah.
Al-Jawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, t.t., Qutb al-Habib al- Gharib, Tausyikh `ala Fath Al-Qarib al-Mujib, Semarang:
Toha Putera.
Al-Jundi, Abdul Halim. 1966. Al-Imam al-Syafi’i: Nasir al-Sunnah wa Wadi’ al- Usul. t.t.p: Dar
al-Qalam.
Al-Jurzani. 1943. Manahil al-‘Irfan. Mesir: Issa al-Bab al-Halabi. Jilid I.
Al-Jurjani,
Al-Syarif Ali bin Muhammad, 1988, Kitab
Al-Ta`rifat, Beirut : Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.
Al-Kahlaniy, Muhammad
bin Ismail, t.t., Subul al-Salam, Bandung
: Dahlan
Al-Khinn, Mustafa Sa’id. 1982. Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawa’id al-Usuliyyah fi Ikhtilaf al-Fiqh. Beirut: Mu`assasah ar-Risalah. Cetakan Pertama.
Al-Khudari, Muhammad, 1965, Tarikh al-Tasyri’ al-Islamy, Mesir: Al- Maktabat Al-Tijariyat al-Kubra.
Al-Mahalli,
Jalaluddin Muhammad bin Ahmad, 2001, Kanz
al-Raghibin Syarh Minhaj al-Talibin, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
cet. 1.
Al-Mishri,
Ibnu Manzhur Abu al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin al-Afriqi, t.t., Lisan al-`Arab, Beirut : Dar al-Shadir,
jilid VII
Al-Nawawi, Muhyiddin
Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri, t.t., Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi`in, Beirut : Dar al-Fikr, cet 1.
Al-Qardhawi,
Yusuf. 1987. al-Ijtihad fi asy-Syariah
al-Islamiyyah ma’a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad
al-Mu’asir, terj. Ahmad Syathari. Jakarta: Bulan Bintang.
Al-Qardhawi, Yusuf, 1994, Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw, terj.
Muhammad al-Bagir, Bandung
: Kharisma.
Al-San’ani,
1988, Subul al-Salam, Beirut : Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid IV. Al-Syafi`I, 1961, al-Umm, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, jilid VII.
Al-Syarbini, Muhammad
al-Khatib, t.t., Mughni al-Muhtaj,
Beirut : Dar al-Fikr.
Al-Utsaimin,
Muhammad bin Shalih, 2014, Fikih Thaharah,
Jakarta : Darus Sunnah Press, cet 1.
Al-Zarqani, Muhammad ‘Abd al-Azim, Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulm al-Qur’an, Beirut : Dar al-Fikr, Juz 1.
Anis, Ibrahim, dkk.,
1972, al-Mu`jam al-Wasit, Mesir:
Majma` al-Lughah al- Arabiyyah.
Ash-Shiddieqy, Hasbi,
1954, Kuliah Ibadah, Jakarta : Bulan
Bintang.
Asy-Sarkhasi,
Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, 1382 H, Usul as- Sarkhasi, Beirut: Dar al-Ma’rifah, Jilid I.
Asy-Syatibi, Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim
ibn Musa, t.t., Al-Muwafaqat fi Usul
al-Ahkam, t.t.p: Dar al-Fikr, Jilid IV.
Asy-Syaukani, 1349 H, Irsyad
al-Fuhul, t.t.p.: Matba’ah Sabih.
Audah, Abdul Qadir, 1992, al-Tasyri` al-Jina`I al-Islami Muqaranan bi
Al- Qanun Al-Wad`I, Beirut : Mu`assasah al-Risalah. Jilid !!
Az-Zuhaili, Wahbah.
1986a. Usul al-Fiqh al-Islami. Damaskus:
Dar al-Fikr.
Jilid
I. Cetakan Kelima Belas.
Az-Zuhaili, Wahbah. 1986b. Usul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.
Jilid II.
Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, Darajat,
Zakiah, 1995, Ilmu Fiqh, Yogyakarta :
Dana Bhakti Wakaf, jilid 2.
Dikbud, Dep, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :
Balai Pustaka,
Ghazaly, Abd.Rahman,
2006, Fiqh Munakahat, Jakarta :
Kencana.
Ghazali, Imam, dan A.Ma`ruf Asrori (eds), 2004, Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual
Hukum Islam, Surabaya: Diantama.
Hakim,
Abdul Hamid, t.t. Al-Bayan, Jakarta
:Bulan Bintang
Hamid, Abdul, Beni Ahmad Saebani, 2009,
Fiqh Ibadah, Bandung:Pustaka Setia,
Haroen, Nasrun.
1997. Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos
Wacana Ilmu. Hasaballah, Ali. t.t. Usul
at-Tasyri’ al-Islami. Kairo: Dar al-Ma’arif. Ibn Manzur. t.t. Lisan al-Arab. Beirut: Dar as-Sadr. Jilid
III.
Irfan,
M. Nurul, Masyrofah, 2013, Fiqh Jinayah,
Jakarta : Amzah.
Khallaf, Abdul Wahab.
1968. Ilm Usul al-Fiqh. t.t.p.:
Ad-Dar al-Kuwaitiyyah.
Cetakan
Kedua.
Ma`luf, Louis, 1986, al-Munjid fi al-Lughat wa al-A`lam, Beirut
: Dar al- Masyriq Mathba`ah Katolikiyah,
Mughniyah, Muhammad
Jawad ,1996, Fiqih Lima Mazhab,
Jakarta: Lintera,
Mukhtar,
Kamal, dkk. 1995a. Ushul Fiqh I. Yogyakarta:
Dana Bhakti Wakaf.
Mukhtar,
Kamal, dkk. 1995b. Ushul Fiqh II. Yogyakarta:
Dana Bhakti Wakaf. Munawwir, A.W., 1997, Kamus
al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
Surabaya
: Pustaka Progressif, cet. 14.
Nasution, Zakaria,
t.t., Dasar-dasar Agama Islam,t.tp.
Qasim, M.Rizal, 2009, Pengalaman
fikih, Solo : PT. Tiga Serangkai Mandiri. Rahman, Asjmuni A. 1986. Qaidah-Qaidah Fiqih. Jakarta: Bulan
Bintang.
RI, Depag, 1984/ 1985, Ilmu Fiqh, Jakarta : Dirjen Bimbaga
Islam. Rifa`I, moh, 1978, Fiqih Islam,
Semarang : PT.Karya Toha Putra
Rida,
Muhammad Rasyid. t.t. Tafsir Al-Qur`an
Al-Hakim Al-Masyhur bi Tafsir Al-Manar. Lebanon: Dar Al-Ma’rifah. Jilid II.
Rasjid,
Sulaiman,
2015, Fiqih Islam, Bandung : Sinar Baru
Algensindo Offset, cet. 70
Rofiq,
Ahmad, 2001, Fiqh Mawaris, Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada.
Rusyd, Ibnu, t.t., Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut : Dar al-Fikr.
Sabiq,
Sayyid, 1995, Fiqih Sunnah, Beirut :
Dar al-Fikr, jilid I,
Salih, Muhammad Adib. 1984. Tafsir an-Nusus fi al-Fiqh al-Islami. Beirut:
Al- Maktab al-Islami. Jilid I.
Shihab,
M. Quraish. 1994. Membumikan Al-Qur`an.
Bandung: Mizan.
Sinaga, Ali Imran, 2011, Fikih II, Bandung: Citapustaka Media
Perintis. Sudarko, 2008, Fiqih, Semarang
: Aneka Ilmu,
Syafe’i, Rahmat. 1999. Ilmu
Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia.
Syalabi, Ahmad. 1984. Sejarah
Pembinaan Hukum Islam, terj. Abdullah Badjirei, Jakarta: Jaya Murni.
Syarifuddin, Amir, 1997, Ushul
Fiqh I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, cet. 1. Syukur, M. Asywadie. 1990. Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih. Surabaya:
P.T. Bina Ilmu.
Tim
Penyusun Text Book. 1981. Pengantar Ilmu
Fiqh. Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Pusat.
Walindayani, 2012, Perkawinan
Beda Agama, ed. Pagar Hasibuan, Fikih
Perbandingan, Dalam Masalah-masalah Aktual, Bandung : Cita Pustaka Media
Perintis.
Wer, Hans. 1980. A
Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-English.
London: Macdonald
& Evans Ltd. Cetakan Ketiga.
Ya`la, Abu, 1983, al-Ahkam al-Sultaniyyah, Beirut : Dar
al-Kutub al-Ilmiyyah.
Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (a) Malik Hayatuh wa ‘Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby.
Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (b) Ibn Hazam: Hayatuh wa’Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby.
Zahrah, Muhammad Abu. 1952. (c) Abu Hanifah: Hayatuh wa ‘Asruh- `Ara`uh wa Fiqhuh. Kairo: Dar
al-Fikr al-‘Araby. Cetakan kedua.
Zahrah, Muhammad Abu. t.t. (d) Al-Imam Zaid: Hayatuh wa ‘Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh. Kairo: Dar
al-Fikr al-‘Araby.
Zahrah,
Muhammad Abu. t.t. (e) Ibn Taimiyyah:
Hayatuh wa ‘Asruh-`Ara`uh wa Fiqhuh. t.t.p.: t.p.
Zainuddin,Djedjen, dan Mundzier
Suparta, 2008, Pendidikan Agama Islam
Fikih, Semarang: Toha Putra.